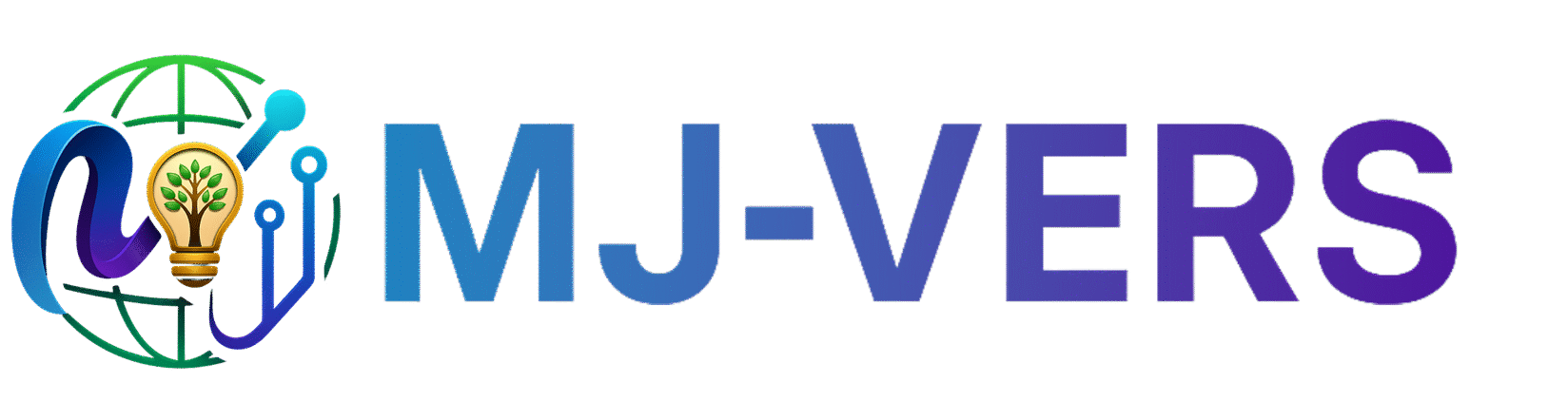Dalam lanskap sosial-politik kontemporer, salah satu fenomena yang paling mencemaskan adalah krisis kepercayaan publik terhadap institusi. Krisis ini bukan sekadar penurunan rasa hormat atau skeptisisme biasa, melainkan erosi mendalam terhadap fondasi sosial yang mestinya menjadi pengikat kehidupan bersama.
Institusi, baik negara, lembaga pendidikan, media, idealnya berfungsi sebagai penjaga nilai, pengatur keteraturan, dan pemberi legitimasi moral. Namun ketika publik merasa dikhianati, dicederai, atau sekadar diabaikan, institusi yang seharusnya menjadi tiang penyangga peradaban justru tampak rapuh, bahkan runtuh.
Kepercayaan merupakan modal sosial yang tak terlihat, tetapi menentukan kelangsungan masyarakat. Robert Putnam dalam Bowling Alone menegaskan bahwa kepercayaan adalah inti dari social capital yang memungkinkan kerjasama sosial dan kohesi kolektif. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan legitimasi, kebijakan kehilangan penerimaan, dan kepemimpinan kehilangan arah. Fenomena distrust publik terhadap institusi hari ini bisa dibaca sebagai tanda alarm bahwa modal sosial kita sedang terkikis secara serius.
Faktor penyebab krisis ini bersifat kompleks dan multidimensi. Pertama, maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik nepotisme telah menggerogoti moralitas institusional. Kedua, ketidakmampuan institusi merespons dinamika zaman, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi, membuat publik melihat adanya jarak antara ideal dan realitas. Ketiga, arus informasi yang tidak terkendali, dengan banjir hoaks dan framing media, membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara kebenaran dan manipulasi. Dalam situasi demikian, rasa percaya perlahan-lahan terkikis, digantikan oleh sinisme yang meluas.
Refleksi atas kondisi ini menuntun kita pada pertanyaan yang lebih mendasar apakah institusi hanya sebatas struktur formal dengan regulasi dan kewenangan, ataukah ia juga organisme moral yang bernafas bersama masyarakat? Jika institusi hanya dipahami sebagai mesin birokrasi, maka ia akan selalu jauh dari rakyat, kaku, dan dingin. Sebaliknya, bila institusi dipahami sebagai rumah bersama yang hidup dari kepercayaan warga, maka integritas, transparansi, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendasar untuk bertahan.
Dari perspektif sosiologis, runtuhnya kepercayaan publik menandakan hilangnya “narasi besar” yang dulunya menjadi sumber legitimasi. Di masa lalu, institusi negara berdiri kokoh dengan narasi pembangunan, Institusi dihormati karena dianggap pemegang kebenaran dan media dipercaya sebagai penyampai suara rakyat. Namun dalam era pasca-modern yang penuh fragmentasi, narasi besar ini retak. Masyarakat tidak lagi menerima kebenaran secara taken-for-granted, melainkan terus mempertanyakan siapa yang diuntungkan di balik setiap kebijakan, fatwa, atau pemberitaan.
Lebih jauh, krisis kepercayaan publik juga berdampak pada psikologi sosial. Ketika warga merasa tidak bisa mempercayai institusi, lahirlah kecenderungan apatis, menarik diri dari ruang publik, bahkan lahir gerakan perlawanan dalam bentuk counter public. Fenomena distrust ini pada gilirannya melahirkan siklus berbahaya yaitu semakin publik tidak percaya, semakin institusi bertahan dengan otoritarianisme atau formalitas kosong, dan semakin jauh pula jarak antara penguasa dan rakyat.
Namun refleksi ini tidak boleh berhenti pada pesimisme. Justru di tengah krisis, terdapat peluang untuk membangun ulang fondasi kepercayaan. Pertama, institusi perlu menata ulang komitmen etis dengan menegakkan akuntabilitas yang nyata, bukan simbolis. Kedua, transparansi harus menjadi prinsip, bukan sekadar formalitas laporan tahunan. Ketiga, dialog yang setara dengan masyarakat perlu dibuka, sebab kepercayaan tidak lahir dari instruksi satu arah, melainkan dari perjumpaan yang tulus antara aspirasi rakyat dan respons institusional.
Dalam konteks Indonesia, membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi merupakan tugas peradaban. Negara yang besar tidak hanya ditopang oleh kekayaan alam atau kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi moral dan kepercayaan rakyatnya. Tanpa itu, kebijakan secanggih apa pun akan kehilangan makna, karena rakyat hanya melihatnya sebagai instrumen kekuasaan, bukan pengabdian.
Akhirnya, krisis kepercayaan publik terhadap institusi adalah cermin bagi kita semua. Institusi bukan entitas asing, ia hidup dari legitimasi yang kita berikan. Ketika publik merasa dikhianati, sesungguhnya institusi telah gagal merawat jiwanya sendiri. Jalan ke depan menuntut keberanian untuk menumbuhkan kembali nilai dasar. yaitu integritas, keterbukaan, dan kejujuran. Hanya dengan itu, jurang antara institusi dan masyarakat bisa dijembatani, dan modal sosial yang hilang perlahan bisa dipulihkan.