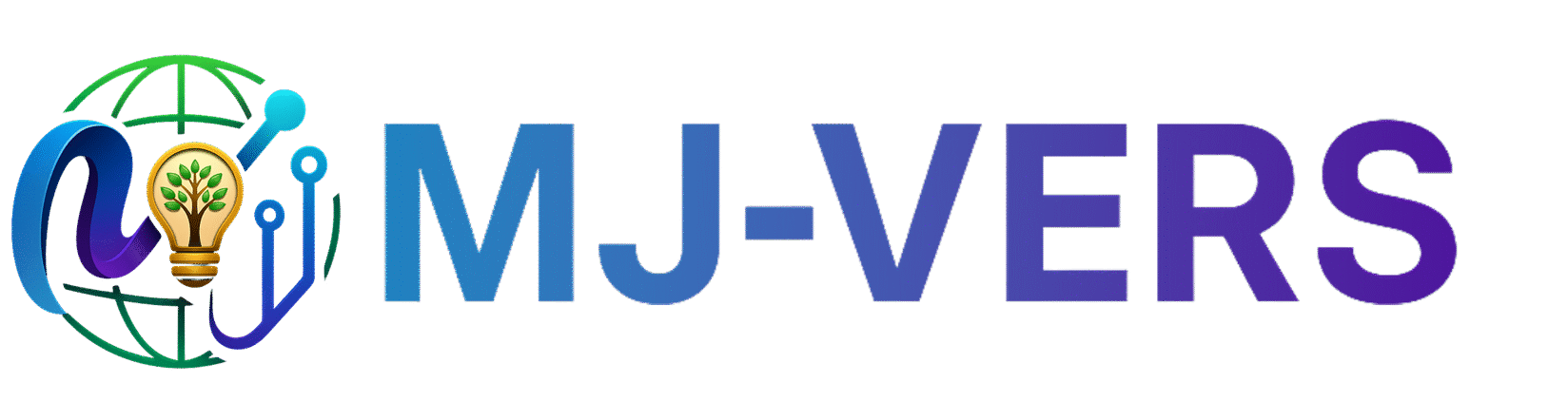Pemerintah dengan bangga mengumumkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp 757,8 triliun. Angka ini disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan hampir 10 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari perspektif makro, klaim ini seolah menunjukkan komitmen kuat negara untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun, pertanyaan kritis muncul, apakah angka besar tersebut benar-benar mencerminkan besarnya investasi negara pada kualitas pendidikan?
Secara teori, amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) memang mengharuskan negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Pada titik ini, pemerintah terlihat patuh terhadap konstitusi. Tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, struktur penggunaan anggaran menunjukkan bahwa “besar di angka” belum tentu berarti besar di esensi. Sebab, di balik retorika angka jumbo, distribusi pos-pos belanja ternyata lebih condong ke belanja rutin dan program sosial ketimbang inti pembelajaran.
Dari Rp 757,8 triliun tersebut, dua pos raksasa menyedot mayoritas dana, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun dan gaji serta tunjangan guru-dosen Rp 178,7 triliun. Jika dijumlah, kedua pos ini menghabiskan Rp 513,7 triliun atau sekitar 67,7% dari total anggaran pendidikan. Keduanya memang penting, gizi menunjang kesehatan peserta didik, dan gaji guru menjamin keberlangsungan sistem. Namun, alokasi semacam ini masih masuk kategori belanja rutin dan sosial, bukan belanja akademis murni.
Baru setelah mengurangi dua pos besar itu, kita menemukan alokasi yang lebih dekat ke jantung pendidikan. Misalnya, BOS sebesar Rp 64,3 triliun, BOP PAUD Rp 5,1 triliun, renovasi sekolah Rp 22,5 triliun, BOPTN Rp 9,4 triliun, Sekolah Rakyat Rp 24,9 triliun, dan Sekolah Unggulan Rp 3 triliun. Ditambah dengan beasiswa dan program akses seperti KIP Kuliah Rp 17,2 triliun, PIP Rp 15,6 triliun, serta LPDP Rp 25 triliun. Jika dikalkulasi, total belanja murni pendidikan hanya mencapai Rp 187 triliun.
Artinya, hanya sekitar 24,7% dari total anggaran pendidikan 2026 yang benar-benar menyentuh ruang kelas, infrastruktur, dan akses belajar mahasiswa maupun siswa. Selebihnya, hampir tiga perempat anggaran justru berputar di area gizi dan belanja pegawai. Dengan kata lain, hanya satu dari empat rupiah “anggaran pendidikan” yang secara langsung dialokasikan untuk memperkuat kualitas pembelajaran.
Jika angka Rp 187 triliun ini kita distribusikan secara merata ke 38 provinsi, maka setiap provinsi hanya menerima rata-rata Rp 4,9 triliun untuk seluruh komponen murni pendidikan. Lebih jauh lagi, jika diturunkan ke 416 kabupaten, alokasinya sekitar Rp 449 miliar per kabupaten. Sementara jika dihitung ke seluruh 514 kabupaten/kota, maka nilainya bahkan lebih kecil, yaitu Rp 363 miliar per daerah. Bandingkan dengan kebutuhan nyata seperti pembangunan sekolah, perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu guru, dan beasiswa yang terus bertambah.
Ketika angka Rp 757,8 triliun diumumkan secara nasional, publik tentu terkesan dengan besarannya. Namun, realitas di lapangan berbeda. Di satu sisi, guru masih sering mengeluhkan minimnya fasilitas, sekolah di daerah 3T masih kesulitan mendapatkan akses internet, dan perguruan tinggi negeri masih bergulat dengan keterbatasan laboratorium serta riset. Ironisnya, pos-pos belanja yang seharusnya menjawab persoalan tersebut justru menjadi porsi terkecil dari keseluruhan anggaran.
Pola semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai framing anggaran. Apakah benar negara telah menggelontorkan dana besar untuk pendidikan, ataukah “angka jumbo” itu hanya menjadi kosmetik fiskal yang menutupi kenyataan bahwa dana murni pendidikan tetap terbatas? Lebih jauh, apakah program seperti MBG, meski bermanfaat, seharusnya dikategorikan sebagai bagian dari “anggaran pendidikan” atau sebagai program sosial kesehatan?
Dalam perspektif akademik, kejujuran fiskal menjadi kunci. Jika label “anggaran pendidikan” terus dipakai untuk menutupi dominasi belanja rutin dan sosial, maka publik akan terjebak pada persepsi semu bahwa negara telah memenuhi kewajiban konstitusi. Padahal, realitanya investasi langsung pada kualitas pembelajaran masih jauh dari memadai. Ini bisa menjelaskan mengapa meskipun anggaran terus meningkat, hasil asesmen internasional seperti PISA belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dengan demikian, kesimpulan reflektifnya jelas bahwa anggaran pendidikan 2026 memang terbesar dalam sejarah, tetapi besarnya lebih pada angka nominal ketimbang esensi. Jika hanya seperempat dana yang benar-benar murni untuk pendidikan, maka klaim “terbesar” lebih tepat disebut framing ketimbang substansi. Untuk itu, tantangan ke depan adalah memastikan agar label anggaran pendidikan benar-benar mencerminkan investasi pada mutu belajar, bukan sekadar pembiayaan rutin yang membesar dari tahun ke tahun.