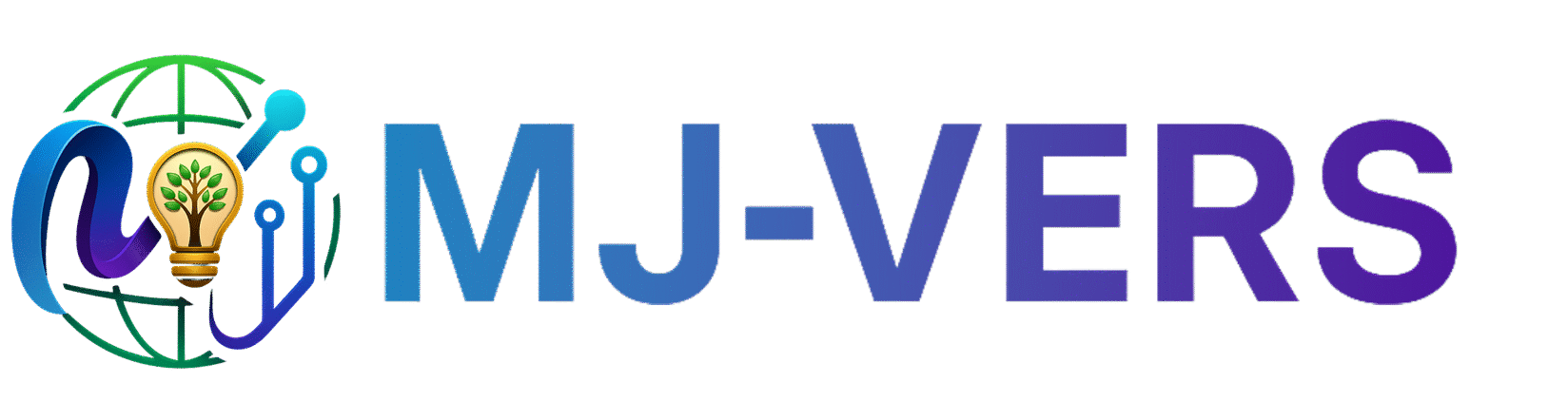Di tengah derasnya arus informasi digital, ruang komunikasi publik lembaga seharusnya menjadi mercusuar pengetahuan. Media resmi, baik berbentuk situs web, kanal berita, maupun akun media sosial, memiliki posisi strategis dalam membentuk cara masyarakat memahami kebijakan, nilai, dan arah pembangunan sosial. Dalam ekosistem digital yang penuh disinformasi, kehadiran media resmi semestinya menjadi sumber rujukan terpercaya yang menuntun publik menuju literasi, bukan sekadar menambah kebisingan visual di dunia maya.
Namun, ketika media resmi hanya digunakan untuk memperlihatkan aktivitas seremonial dan memperkuat citra figur pimpinan, nilai edukatif yang seharusnya terkandung di dalamnya pun memudar. Media menjadi panggung, bukan ruang belajar. Ia berhenti menjadi sarana dialog publik yang mencerahkan dan berubah menjadi galeri pencitraan yang terputus dari makna sosial. Padahal, di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar dokumentasi, namun mereka mendambakan narasi yang menumbuhkan pemahaman dan kesadaran. Dari titik inilah refleksi ini berangkat meninjau kembali hakikat media resmi lembaga sebagai cermin nilai, bukan sekadar simbol seremonial.
Media sosial resmi lembaga atau instansi, sejatinya, bukan sekadar ruang dokumentasi aktivitas birokrasi. Ia adalah wajah institusional yang berbicara langsung kepada publik, menampilkan nilai, etika, dan orientasi sosial dari lembaga yang menaunginya. Dalam konteks masyarakat digital yang haus informasi, media resmi seharusnya berfungsi sebagai instrumen literasi yang mendidik, mencerdaskan, dan menumbuhkan kesadaran kritis publik terhadap berbagai isu sosial dan kebijakan yang berdampak nyata pada kehidupan bersama.
Namun kenyataan yang mengemuka justru memperlihatkan kecenderungan yang memprihatinkan. Banyak akun resmi lembaga publik berubah menjadi ruang seremonial yang monoton, dipenuhi unggahan foto pimpinan menghadiri kegiatan, memotong pita, atau memberikan sambutan tanpa narasi edukatif yang berarti. Masyarakat disuguhi potret formalitas yang lebih menonjolkan figur ketimbang makna. Akibatnya, media resmi kehilangan relevansinya sebagai kanal komunikasi yang mendidik. Ia berfungsi seperti papan pengumuman elektronik, bukan sumber pengetahuan publik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga belum memahami bahwa komunikasi publik adalah bagian dari tanggung jawab moral kelembagaan. Dalam teori komunikasi modern, setiap bentuk penyiaran informasi lembaga memiliki dimensi etis antaralain apakah pesan yang disampaikan memperluas pemahaman masyarakat, atau sekadar memperkuat simbol kekuasaan. Ketika media resmi lebih sibuk menonjolkan seremoni internal, maka ruang digital kehilangan nilai transformasinya, ia gagal menjalankan fungsi sosial yang seharusnya melekat pada lembaga publik.
Padahal, di era disrupsi informasi, kepercayaan publik terhadap institusi dibangun bukan melalui kemegahan acara, melainkan melalui transparansi makna. Masyarakat lebih menghargai lembaga yang mampu menjelaskan alasan, tujuan, dan dampak dari setiap kebijakan atau kegiatan, bukan sekadar menampilkan potret pejabat tersenyum di depan kamera. Dalam konteks ini, kehadiran media resmi seharusnya menjadi sarana edukasi publik yaitu menjelaskan proses di balik keputusan, memberi ruang partisipasi warga, dan membentuk pemahaman kolektif tentang arah pembangunan sosial.
Setiap unggahan di media resmi memiliki kekuatan simbolik. Ia dapat membentuk persepsi, menggiring opini, bahkan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena itu, pengelolaan media sosial lembaga tidak boleh bersandar pada logika seremonial, melainkan pada paradigma edukatif dan etis. Narasi yang disusun mesti menempatkan publik sebagai subjek belajar, pembaca yang berhak mendapatkan makna, bukan sekadar penonton dari parade birokrasi.
Kelemahan yang sering muncul adalah minimnya kapasitas literasi digital di kalangan pengelola lembaga. Banyak pengelola media resmi masih memandang tugas mereka sebatas “mengunggah kegiatan”, bukan “menyampaikan pesan yang bermakna”. Akibatnya, mereka gagal membangun jembatan antara aktivitas kelembagaan dengan nilai edukatif yang dapat dirasakan masyarakat. Padahal, setiap kegiatan lembaga memiliki potensi pembelajaran jika dikomunikasikan dengan cara yang tepat, reflektif, dan kontekstual.
Di sinilah pentingnya transformasi paradigma komunikasi institusional: dari seremonial menuju edukatif. Sebuah lembaga yang berorientasi pada pembelajaran publik akan menampilkan pesan-pesan yang menginspirasi, mengajak berpikir, dan membangun kesadaran sosial. Misalnya, kegiatan pelatihan tidak hanya diberitakan sebagai acara, tetapi dijelaskan pula dampaknya bagi peningkatan kompetensi masyarakat. Kunjungan pejabat bukan hanya foto seremonial, melainkan momentum berbagi gagasan dan nilai.
Tanggung jawab moral lembaga terhadap literasi publik tidak bisa diabaikan. Ketika masyarakat semakin terpapar arus informasi yang tidak selalu valid, media resmi menjadi benteng terakhir penyampaian kebenaran. Jika kanal-kanal tersebut diisi dengan konten dangkal, maka lembaga turut memperburuk ekologi pengetahuan digital. Sebaliknya, jika media lembaga menyajikan informasi yang akurat, reflektif, dan mendidik, maka ia berperan sebagai agen literasi digital nasional.
Perubahan fungsi ini menuntut kepemimpinan yang visioner. Pemimpin lembaga perlu memandang media bukan sebagai alat promosi diri, tetapi sebagai sarana pendidikan sosial. Ia harus memberi teladan dengan menekankan nilai-nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam setiap komunikasi publik. Pemimpin yang peka akan memahami bahwa citra sejati lembaga tidak dibangun oleh banyaknya foto dirinya, melainkan oleh manfaat yang dirasakan publik dari pesan yang disampaikan.
Dalam kerangka pendidikan publik, media resmi memiliki posisi strategis untuk membentuk budaya berpikir kritis masyarakat. Ketika lembaga menjelaskan latar belakang kebijakan, dampak sosial, atau nilai moral di balik suatu kegiatan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga peserta aktif dalam memahami realitas sosial. Inilah yang disebut komunikasi partisipatif edukatif, suatu bentuk komunikasi yang membangun kesadaran, bukan sekadar menyebar kabar.
Selain itu, media resmi juga berpotensi menjadi ruang refleksi kolektif. Melalui narasi yang jujur dan inklusif, lembaga dapat mengajak masyarakat merenungkan isu-isu publik seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan kemanusiaan. Konten semacam ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui seremoni: ia menanamkan nilai dan membentuk karakter masyarakat digital. Di tengah krisis etika komunikasi di dunia maya, pendekatan reflektif dari lembaga resmi bisa menjadi contoh nyata bahwa informasi publik dapat bermartabat.
Transformasi media resmi menuju fungsi edukatif tidak bisa dilakukan secara instan. Ia membutuhkan kebijakan komunikasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan terhadap nilai-nilai literasi. Setiap lembaga perlu memiliki pedoman etika digital yang menegaskan orientasi mendidik dalam setiap unggahan. Dengan demikian, media resmi menjadi bagian dari strategi pendidikan publik, bukan sekadar pelengkap administratif kegiatan.
Kita perlu menyadari bahwa keberadaan media resmi adalah amanah sosial. Ia mengandung tanggung jawab untuk menebar kebenaran dan menumbuhkan kesadaran. Jika disalahgunakan sebagai panggung seremonial, lembaga justru mencederai kepercayaan publik. Namun jika dikelola dengan visi edukatif, ia akan menjadi instrumen pencerahan yang melampaui batas institusi menjadi ruang belajar bersama di tengah kebisingan digital.
Pada akhirnya, esensi keberadaan media resmi tidak diukur dari banyaknya unggahan, tetapi dari seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan pengetahuan dan kematangan sosial masyarakat. Media resmi yang mendidik adalah media yang menyentuh nalar publik, mengajak berpikir, dan menumbuhkan empati. Di sanalah nilai sejati komunikasi kelembagaan ditemukan, bukan pada seremoni yang dipamerkan, melainkan pada makna yang ditanamkan.
Jika lembaga-lembaga di negeri ini mulai menata ulang arah komunikasinya, menjadikan setiap unggahan sebagai sarana literasi, bukan sekadar dokumentasi, maka kita sedang bergerak menuju peradaban digital yang cerdas dan bermartabat. Sebuah bangsa tidak hanya dibangun dengan kebijakan, tetapi juga dengan narasi-narasi yang mendidik, menumbuhkan, dan menghidupkan kesadaran sosial di ruang maya yang kini menjadi wajah utama dunia nyata.