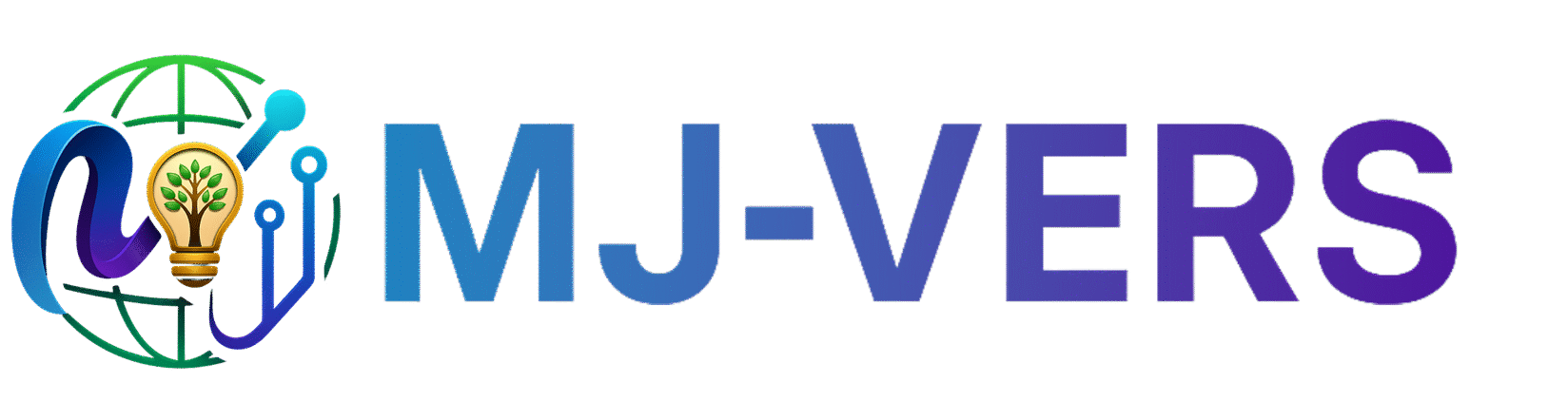Pernyataan Menteri Agama pada pembukaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Batch 3, pada 3 September 2025, bahwa guru adalah profesi mulia dan tidak boleh semata-mata dijalani demi mencari uang, menyentuh inti etika profesi kependidikan.
Dalam sambutannya beliau menegaskan:
“Guru itu tujuannya mulia, bagaimana memintarkan anak orang itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah.”
Guru memang memiliki dimensi spiritual yang mendalam, yaitu amal jariyah yang pahalanya tidak terputus, bahkan disebut sebagai profesi yang mempersiapkan generasi masa depan. Namun, dalam konteks sosial-ekonomi saat ini, narasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas kesejahteraan guru yang masih jauh dari harapan.
Secara normatif, apa yang disampaikan Menteri Agama memiliki dasar kuat. Guru memang seharusnya digerakkan oleh panggilan jiwa, bukan sekadar oleh imbalan materi. Dalam khazanah Islam, pendidikan adalah ladang amal yang nilainya tidak ternilai. Akan tetapi, pemaknaan moral ini tidak boleh berhenti pada seruan idealisme, sebab guru tetaplah manusia yang memiliki kebutuhan jasmani dan sosial yang harus terpenuhi.
Sejarah Islam sendiri menunjukkan bahwa kemuliaan profesi guru tidak pernah dibiarkan tanpa penghargaan material. Pada masa Abbasiyah, guru di kuttab menerima gaji 1–5 dinar emas per bulan, sementara guru besar di Madrasah Nizamiyah bisa memperoleh 200–300 dinar per bulan, jumlah yang sangat besar bahkan setara pejabat tinggi. Gaji itu berasal dari dana wakaf dan kas negara, menunjukkan bahwa penghormatan spiritual selalu dibarengi penghargaan material yang memadai.
Praktik di dunia Arab modern juga menunjukkan kesinambungan prinsip tersebut. Di Uni Emirat Arab, gaji guru bisa mencapai Rp50–85 juta per bulan, bahkan hingga Rp158 juta di sekolah internasional, lengkap dengan tunjangan rumah, kesehatan, dan tiket perjalanan. Di Arab Saudi, guru SD bisa menerima Rp18 juta per bulan, sementara guru SMA hingga Rp44 juta. Negara-negara seperti Qatar memberikan paket serupa, membuktikan bahwa profesi guru dihormati secara layak.
Bahkan figur ulama seperti Syaikh Abdul Rahman as-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, pernah menyatakan bahwa beliau tidak tahu gajinya karena pemerintah memberinya cek kosong untuk diisi sesuai kebutuhan. Hal ini melambangkan penghormatan negara terhadap ulama dan pendidik, bukan hanya dalam simbol tetapi dalam kesejahteraan yang nyata. Dengan kata lain, ikhlas bukan berarti miskin, keikhlasan tetap bisa beriringan dengan kesejahteraan yang dijamin negara.
Kontras dengan itu, realitas di Indonesia masih menyisakan luka mendalam. Jutaan guru honorer di berbagai daerah masih digaji ratusan ribu rupiah per bulan. Ada yang menerima Rp300 ribu, bahkan lebih rendah. Kondisi ini membuat mereka harus mencari pekerjaan sampingan sebagai pengemudi ojek online, pedagang kecil, atau les privat, semata untuk menutup kebutuhan dasar. Bagaimana mungkin guru bisa sepenuhnya fokus mendidik jika sebagian besar energi tercurah untuk bertahan hidup?
Di titik ini, seruan idealisme yang menuntut guru ikhlas justru berisiko menjadi bentuk romantisasi yang mengabaikan realitas struktural. Keikhlasan seolah dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap keterbatasan sistemik. Padahal, ketika guru dipaksa ikhlas dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan, yang lahir bukan dedikasi murni, melainkan keletihan yang berujung pada menurunnya kualitas pendidikan.
Negara dan lembaga pendidikan seharusnya belajar dari sejarah dan praktik internasional. Guru adalah profesi strategis, karena dari tangan mereka lahir generasi bangsa. Oleh karena itu, negara harus menghadirkan sistem kesejahteraan yang memadai, gaji layak, tunjangan profesi yang adil, jaminan sosial, serta penghargaan yang sesuai dengan pengabdian mereka. Tanpa kebijakan struktural ini, ajakan ikhlas hanya akan menjadi wacana kosong.
Sertifikasi guru, sebagaimana dicanangkan dalam PPG Batch 3, patut diapresiasi sebagai langkah maju. Namun, lonjakan jumlah peserta PPG hingga ratusan ribu tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan. Sertifikasi hanya bermakna jika diikuti dengan peningkatan nyata pada pendapatan, jaminan kerja, dan pengembangan profesional yang berkesinambungan. Tanpa itu, PPG hanya akan menjadi prestasi administratif, bukan jawaban substantif.
Pada akhirnya, pernyataan Menteri Agama mengandung kebenaran moral yang patut disepakati, guru memang profesi mulia yang harus dijalani dengan ikhlas. Namun, kemuliaan guru tidak boleh direduksi menjadi wacana spiritual semata. Negara dan lembaga pendidikan wajib hadir secara nyata untuk memastikan kesejahteraan guru. Barulah tercipta keseimbangan, guru dengan keikhlasan dan dedikasinya, negara dengan perannya menjamin kesejahteraan, dan masyarakat dengan penghargaan yang tulus.