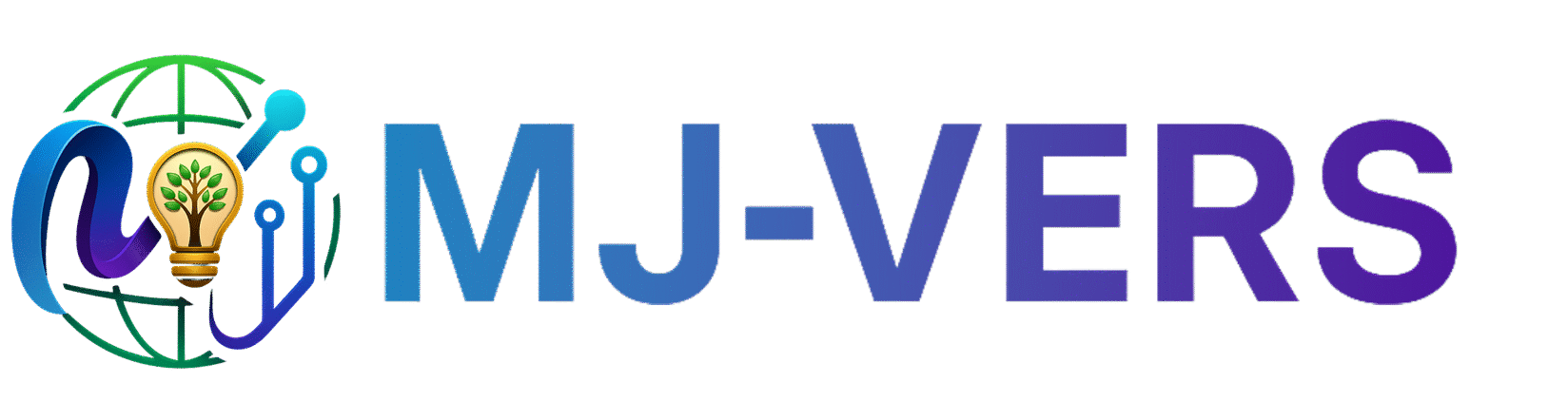Gelombang demonstrasi yang merebak pada penghujung Agustus 2025 menunjukkan bagaimana kemarahan rakyat dapat menjadi energi kolektif yang menggetarkan fondasi politik nasional. Aksi massa bukan sekadar ekspresi spontan, melainkan refleksi dari akumulasi keresahan sosial yang dirasakan publik terhadap perilaku elite politik.
Seperti yang dicatat Associated Press (2025), demonstrasi ini dipicu oleh isu tunjangan dan pernyataan wakil rakyat yang dianggap tidak sensitif, sehingga menyalakan bara kemarahan di jalanan.
Secara akademis, fenomena ini dapat dipahami melalui teori emosi kolektif dalam gerakan sosial. Jasper (1998) menekankan bahwa kemarahan adalah bahan bakar utama aksi protes, karena memberi legitimasi moral bagi massa. Dalam konteks Indonesia, penelitian Ema & Nayiroh (2024) membuktikan bahwa media sosial memperkuat mobilisasi gerakan rakyat dengan cara yang lebih cepat, terbuka, dan langsung. Dengan demikian, demonstrasi Agustus 2025 bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari konektivitas masyarakat digital.
Respon elite politik yang relatif cepat menjadi sorotan. Presiden mengundang pimpinan partai politik serta tokoh lembaga negara untuk membicarakan langkah solutif, lalu sejumlah partai mengambil keputusan menonaktifkan anggota DPR yang menimbulkan kontroversi, efektif berlaku per 1 September 2025 (Detik,31/8/2025Liputan6). Langkah ini memperlihatkan bagaimana tekanan rakyat dan sorotan media dapat mendorong respon nyata dari elite politik.
Dalam kacamata teori political survival (Bueno de Mesquita et al., 2003), tindakan elite ini dapat dimaknai sebagai upaya menjaga legitimasi dan stabilitas. Penonaktifan anggota legislatif bukan hanya bentuk disiplin internal, melainkan strategi untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons keresahan publik. Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki dimensi simbolis sekaligus strategis.
Media sosial berperan besar dalam memperkuat resonansi kemarahan rakyat. Castells (2012) menyebutnya sebagai networks of outrage and hope, di mana dunia digital memungkinkan suara rakyat untuk bergema secara cepat dan luas. Studi terbaru Kahar (2025) menegaskan bahwa bahkan fitur sederhana seperti template di Instagram dapat menjadi sarana efektif mobilisasi protes. Dengan kondisi ini, opini publik tidak bisa lagi dianggap sebagai arus bawah, melainkan sebagai kekuatan utama yang membentuk agenda politik.
Namun, pertanyaan reflektif tetap penting apakah penonaktifan anggota DPR merupakan akuntabilitas sejati atau hanya langkah simbolis? Schedler (1999) membedakan akuntabilitas ke dalam dua aspek, yakni answerability (kesediaan menjawab) dan enforceability (kesediaan menanggung konsekuensi). Jika tindakan elite berhenti pada pencitraan sesaat tanpa reformasi mendalam, maka publik berpotensi melihatnya sebagai bentuk performative accountability.
Penelitian Sitorus (2025) tentang protes digital di Twitter(X) dengan tagar #CabutPermenJHT56Tahun memperlihatkan bahwa jaringan digital menciptakan aktor-aktor baru yang berperan dalam mendorong agenda politik. Hal ini menggarisbawahi bahwa legitimasi politik kini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh struktur formal, melainkan juga oleh interaksi publik yang cair dan dinamis di ruang maya. Dalam konteks 2025, elite politik tidak bisa menutup telinga dari suara yang menggema di media sosial.
Dimensi etika dan kemanusiaan turut memberi warna dalam refleksi ini. Dalam tradisi Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah untuk menghadirkan maslahat bagi umat (al-imamah mashlahat al-ummah). Sementara itu, Rawls (1971) menekankan bahwa keadilan politik hanya bermakna jika benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, langkah elite politik hanya akan bernilai jika membawa dampak keadilan substantif, bukan sekadar meredam amarah sementara.
Implikasi sosial-politik dari peristiwa ini memiliki dua sisi. Dalam jangka pendek, keputusan elite berhasil meredakan sebagian ketegangan dan menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat. Namun dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi presede bahwa rakyat semakin yakin bahwa demonstrasi efektif dalam memengaruhi kebijakan. Utomo & Irwansyah (2024) menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran sentral dalam gerakan menolak penundaan Pemilu, sebuah bukti nyata bahwa ruang publik digital mampu menjadi arena demokrasi.
Akhirnya, penonaktifan beberapa anggota DPR per 1 September 2025 dapat dipandang sebagai momen reflektif dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan kekuatan rakyat dalam mengoreksi elite, sekaligus menantang para pemimpin untuk menghadirkan akuntabilitas yang lebih substansial. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah ini akan menjadi titik balik menuju politik yang bermoral dan etis, ataukah sekadar episode singkat dalam siklus kemarahan dan respon elite? Jawaban itu akan ditentukan oleh konsistensi bangsa dalam menjaga demokrasi yang berpihak pada keadilan.