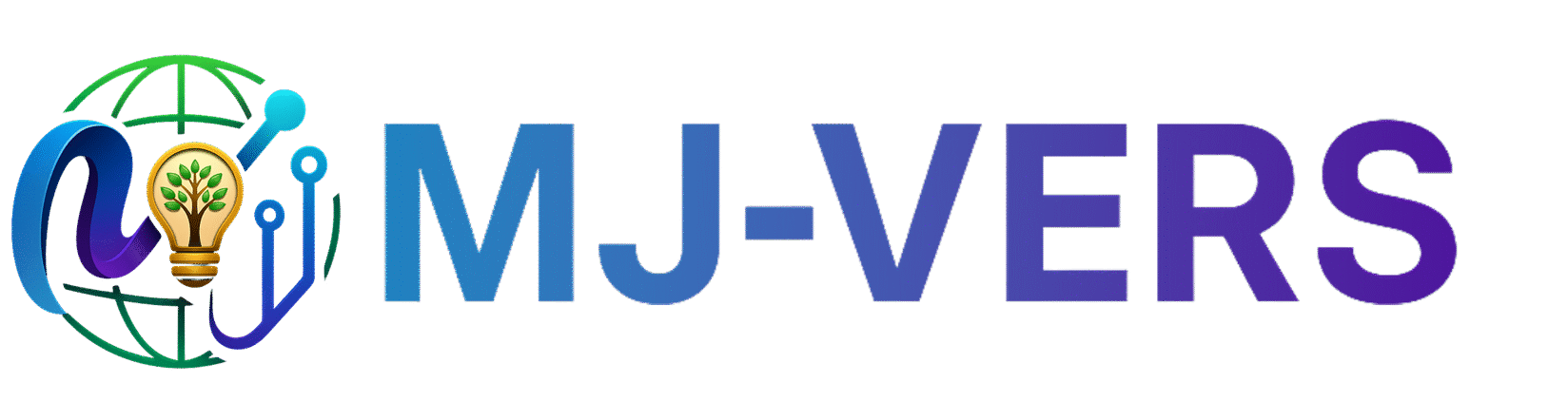Pada suatu pagi di Kabupaten Pati, hamparan alun-alun menyaksikan riuh hati masyarakat yang tersentak oleh kebijakan pajak hingga 250%. Demonstrasi massif menggugah napas kolektif warga yang merasa dizalimi oleh kebijakan yang lahir tanpa dialog. Dalam unjuk rasa 10–13 Agustus 2025, puluhan ribu hingga seratus ribu warga turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan pajak serta pengunduran diri Bupati Sudewo.
Pada suatu pagi di Kabupaten Pati, hamparan alun-alun menyaksikan riuh hati masyarakat yang tersentak oleh kebijakan pajak hingga 250%. Demonstrasi massif menggugah napas kolektif warga yang merasa dizalimi oleh kebijakan yang lahir tanpa dialog. Dalam unjuk rasa 10–13 Agustus 2025, puluhan ribu hingga seratus ribu warga turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan pajak serta pengunduran diri Bupati Sudewo.
Dalam setiap langkah protes, terhimpun kegetiran yang melahirkan kesadaran kolektif: ketidakadilan tidak bisa ditoleransi. Laporan lembaga keuangan internasional mencatat bahwa pajak properti di Indonesia masih sangat rendah hanya sekitar 0,3% dari PDB yang berarti kapasitas fiskal daerah belum maksimal dimanfaatkan.
Dialektika antara fiskalitas dan keadilan terlayar dalam kesunyian politik lokal, pajak yang merenggut pada satu sisi, rasa keadilan yang terbentur pada sisi lain. Rekomendasi kajian ekonomi menyarankan agar tarif maksimal PBB dinaikkan hingga 1% dari nilai aset untuk memperkuat akuntabilitas fiskal dan mendorong transparansi publik.
Namun, transparansi tanpa komunikasi adalah puisi tanpa irama, kosong. Penelitian di Karawang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB, sehingga pemerintah perlu memperkuat sosialisasi secara intensif.
Seperti pelita di lorong birokrasi, akses hukum menjadi jalan bagi warga yang merasa terbebani, namun jalannya masih berliku. Studi di Madiun menyoroti bagaimana mekanisme sanggahan atas NJOP (nilai jual objek pajak) sering kali terhambat oleh ketidakpastian hukum dan keterbatasan aparat fiskal.
Paradigma sejarah pun beriak dalam ingatan: sejak masa kolonial Belanda, pajak atas tanah dan bangunan dirancang untuk keperluan daerah, sebuah legitimasi fiskal yang kini terabai dalam praktik. Kajian administratif mengungkap bahwa, meski potensi PBB tinggi, otonomi fiskal daerah sering terkendala oleh politisasi dan dominasi pusat.
Seolah bergema dari masa lalu, peristiwa Delha Affair tahun 1960 menjadi pengingat pahit bahwa pajak yang tidak adil bisa memantik pemberontakan desa. Konfrontasi di Rote Ndao antara warga dan pemerintah atas beban pajak yang tinggi berakhir dengan kerusuhan dan kehancuran, sebuah tragedi yang mencerminkan pentingnya legitimasi pajak.
Malam di alun-alun Pati seolah merajut kesedihan dan harapan. Puluhan ribu wajah menatap langit, berharap bahwa dialog dan keadilan fiskal akan mengembalikan iman publik. Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan dan berjanji mengembalikan pegawai yang dipecat. DPRD kemudian membentuk panitia khusus untuk menyelidiki aspek kebijakan dan administratif, menandai titik balik dalam hubungan pemerintah-masyarakat.
Namun yang lebih indah dari pembalikan kebijakan adalah kesadaran kolektif tumbuh: pajak bukan momok, melainkan kontrak sosial yang memerlukan musyawarah dan legitimasi. Seorang senator Jawa Tengah menekankan bahwa meski daerah menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan dana pusat, solusi tidak boleh membebani masyarakat, melainkan harus lewat dialog inklusif.
Akhirnya, pelajaran yang tersisa adalah pajak yang adil adalah pajak yang dibarengi transparansi, komunikasi, dan kepatuhan yang dibangun melalui kesadaran warga. Seperti mantra kolektif, masyarakat Pati menyuarakan legitimasi tidak bisa dituntut, ia harus diciptakan bersama.