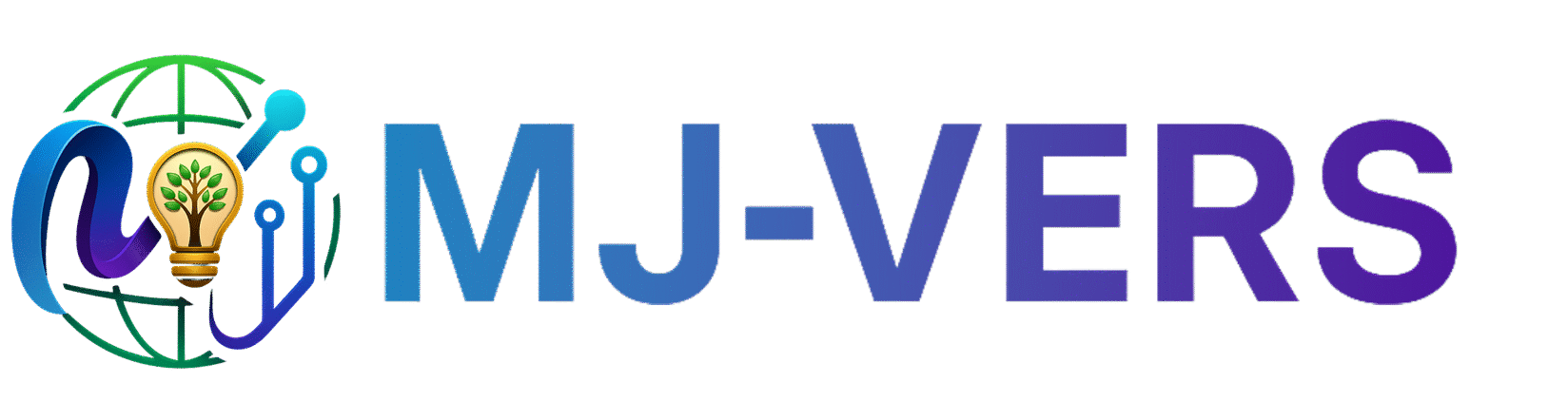Mengapa perbincangan publik begitu sibuk membandingkan SPPG dan guru honorer? Perbandingan itu hampir selalu berujung pada soal gaji dan status. SPPG dianggap lebih “beruntung” karena penghasilannya lebih layak dan peluang diangkat menjadi PPPK terbuka. Sementara guru honorer kembali ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima keadaan. Padahal persoalannya tidak sesederhana siapa lebih diuntungkan. Ada cara berpikir yang keliru dan terus direproduksi tanpa disadari.
Banyak orang lupa bahwa kondisi guru honorer hari ini tidak lahir begitu saja. Rendahnya gaji guru honorer juga merupakan hasil dari cara masyarakat, bahkan guru sendiri, memaknai profesi guru. Guru terlalu lama diposisikan sebagai pengabdi semata. Mengajar dianggap aktivitas sukarela yang mulia, bukan pekerjaan profesional yang layak dibayar pantas. Ketika guru menerima narasi itu, konsekuensinya ikut diterima.
Logika negara berjalan mengikuti realitas sosial. Jika ada banyak orang bersedia mengajar dengan upah minim, negara tidak melihat urgensi untuk berubah. Dalam sistem apa pun, kebijakan akan mengikuti tekanan. Selama tekanan itu rendah, selama pendidikan masih berjalan meski dengan pengorbanan guru honorer, maka negara akan terus berada di zona nyaman. Ini bukan soal kejam atau tidak, tetapi soal mekanisme kekuasaan dan kebijakan.
SPPG hadir dengan kerangka yang berbeda. Mereka direkrut bukan untuk mengabdi secara sukarela, tetapi untuk bekerja secara profesional. Ada kontrak, ada standar, ada kompensasi yang jelas. Tidak ada istilah “ikhlas saja dulu” dalam skema itu. Maka wajar jika negara memperlakukan mereka sebagai tenaga profesional. Perbedaan perlakuan ini bukan ketidakadilan semata, tetapi cerminan cara pandang yang berbeda.
Masalahnya, guru honorer sering kali terjebak dalam romantisasi pengabdian. Pengabdian memang nilai luhur, tetapi ketika dijadikan alasan untuk membenarkan ketidaklayakan, ia berubah menjadi alat penindasan yang halus. Negara tidak perlu menekan, karena guru sudah menekan dirinya sendiri. Dengan dalih ikhlas, sistem yang tidak adil dibiarkan terus berlangsung.
Secara jujur, negara ini kekurangan guru. Namun kekurangan itu tertutupi oleh kenyataan bahwa selalu ada orang yang bersedia menjadi guru honorer. Dalam kondisi seperti itu, negara tidak merasakan krisis yang sesungguhnya. Untuk apa membuka formasi besar-besaran atau mengangkat ASN baru, jika sekolah tetap berjalan dengan guru yang dibayar seadanya?
Bayangkan sejenak sebuah skenario berbeda. Bagaimana jika hampir tidak ada yang mau menjadi guru honorer? Bagaimana jika sekolah benar-benar kekurangan tenaga pengajar? Pendidikan akan terguncang, tekanan publik akan meningkat, dan pemerintah dipaksa mengambil keputusan strategis. Perubahan sering kali lahir bukan dari keluhan, tetapi dari kelangkaan yang tak bisa dihindari.
Selama guru masih mau mengajar dengan upah yang tidak layak, negara tidak akan memiliki insentif kuat untuk berubah. Sistem akan terus memanfaatkan kebaikan hati dan rasa tanggung jawab moral guru. Negara menjadi terbiasa, bahkan “keenakan”. Dalam kondisi seperti ini, niat baik justru menjadi penghambat perbaikan struktural.
Pernyataan ini bukan bermaksud merendahkan guru. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk mengembalikan martabat profesi guru. Namun harus diakui, tanpa sadar guru sering ikut merendahkan dirinya sendiri. Menerima gaji kecil dianggap wajar, karena pengabdian dijadikan alasan utama. Padahal profesionalisme menuntut standar yang jelas.
Guru adalah profesi profesional, sama seperti dokter, insinyur, atau profesi lain yang menuntut keahlian dan tanggung jawab besar. Tidak ada dokter yang diminta “ikhlas saja dulu” demi pengabdian. Mengapa guru harus terus menerima logika itu? Kemuliaan profesi tidak bertentangan dengan profesionalisme, keduanya justru harus berjalan bersama.
Selama ini protes terus dilakukan, tetapi jarang didengar. Mungkin karena protes itu hanya diarahkan ke luar, bukan ke cara berpikir kita sendiri. Kita menuntut negara berubah, tetapi enggan mengubah pola pikir yang membuat ketidakadilan itu langgeng. Kita menuntut pengakuan profesional, tetapi masih mempraktikkan logika sukarela.
Refleksi ini mengajak kita bercermin. Apakah kita benar-benar ingin dihargai sebagai profesional, atau masih nyaman berlindung di balik narasi pengabdian? Apakah kita siap menanggung konsekuensi dari perubahan, atau hanya ingin perubahan tanpa risiko? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak nyaman, tetapi perlu diajukan.
Perbandingan antara SPPG dan guru honorer seharusnya tidak berakhir pada kecemburuan. Ia seharusnya membuka kesadaran tentang perbedaan kerangka berpikir. SPPG diperlakukan profesional karena masuk dengan kerangka profesional. Guru honorer diperlakukan sebaliknya karena sejak awal diposisikan berbeda.
Jika pendidikan ingin diperbaiki secara struktural, maka cara kita memaknai profesi guru harus diubah terlebih dahulu. Perubahan kebijakan selalu mengikuti perubahan kesadaran kolektif. Tanpa itu, regulasi apa pun hanya akan menjadi tambalan sementara.
Maka sebelum terus menyalahkan negara, ada baiknya kita mengajukan satu ajakan bersama: mari berpikir kritis tentang posisi kita sendiri. Tentang pilihan-pilihan yang kita ambil, narasi yang kita pelihara, dan sistem yang tanpa sadar kita legitimasi. Perubahan besar sering kali dimulai bukan dari luar, tetapi dari keberanian mengoreksi cara berpikir kita sendiri.per