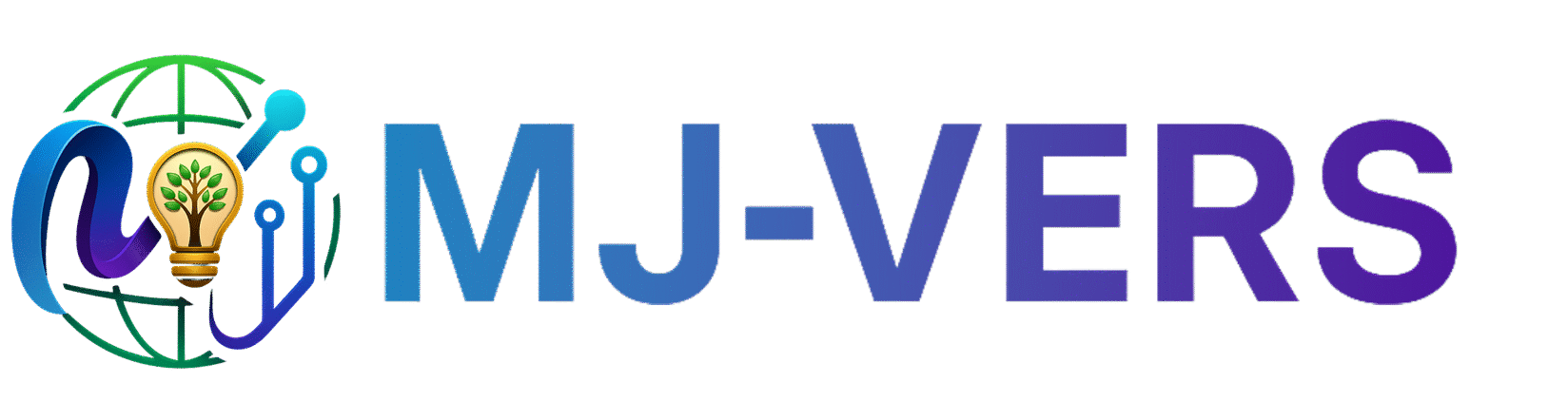Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sesungguhnya memiliki peran yang amat strategis sebagai pondasi pembentukan karakter, intelektualitas, dan kompetensi warga negara. Namun, di tengah derasnya arus perubahan global dan tuntutan abad ke-21, sistem pendidikan kita masih bergulat dengan pola lama yang berorientasi pada hafalan dan ujian.
Proses pembelajaran sering kali berhenti pada kemampuan mengingat, bukan memahami, meniru, bukan mencipta, mencatat, bukan merefleksikan. Ketika anak-anak dibiasakan menjawab dengan cepat tanpa sempat berpikir dalam, pendidikan kehilangan fungsinya sebagai ruang perenungan dan pencarian makna.
Pola belajar yang dominan di sekolah masih mencerminkan paradigma behavioristik klasik menganggap siswa sebagai objek pasif yang menerima stimulus dan harus memberikan respons yang benar. Guru, dalam sistem ini, lebih sering bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal yang menyampaikan informasi, sementara siswa menjadi penerima dan penghafal. Kegiatan seperti diskusi terbuka, proyek kolaboratif, atau riset mini masih dianggap tambahan, bukan kebutuhan. Pola demikian menciptakan ketimpangan antara kemampuan kognitif dasar dengan kecakapan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreasi.
Dampak dari pendekatan semacam ini terasa luas. Siswa dapat menjawab soal ujian dengan benar tetapi kesulitan menerapkan konsep yang sama di dunia nyata. Misalnya, banyak siswa dapat menjelaskan teori ekosistem namun tidak memahami hubungan antara perilaku manusia dan kerusakan lingkungan di sekitar rumahnya. Pembelajaran menjadi terfragmentasi antara teori di sekolah dan praktik kehidupan. Hal ini memperlemah kemampuan adaptasi siswa terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah.
Pemerintah sebenarnya telah mencoba melakukan reformasi melalui penerapan Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini diperkuat dengan konsep Profil Pelajar Pancasila, yang menempatkan nilai-nilai gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis sebagai tujuan utama pembelajaran. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak sekolah menjalankan kegiatan proyek profil sebatas kegiatan simbolik, seperti lomba atau pameran, tanpa perubahan signifikan dalam paradigma mengajar.
Kendala utama terletak pada kesiapan ekosistem pendidikan. Guru belum sepenuhnya dibekali kemampuan pedagogis untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek, refleksi, dan riset. Sebagian besar masih terikat pada beban administrasi, tuntutan kurikulum, serta sistem evaluasi yang berfokus pada nilai kuantitatif. Akibatnya, ruang kreativitas guru dan siswa terbatasi oleh format yang seragam dan birokratis. Dalam konteks inilah, transformasi pendidikan sering kali berhenti di tataran wacana, bukan praksis.
Sementara itu, siswa tumbuh dalam sistem yang mengukur keberhasilan melalui ujian standar dan skor angka. Mereka dilatih untuk mencari “jawaban benar”, bukan mengajukan pertanyaan kritis. Ketika logika ujian menjadi orientasi utama, sekolah kehilangan peran humanistiknya sebagai ruang pembentukan kesadaran, karakter, dan daya cipta. Model pendidikan seperti ini menumbuhkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi sering kali miskin keberanian untuk bereksperimen, gagal, dan mencoba kembali.
Konsekuensi sistemik dari hal ini baru terasa ketika siswa memasuki perguruan tinggi. Banyak mahasiswa mengalami keterkejutan kognitif karena terbiasa dengan instruksi tunggal dan bukan eksplorasi mandiri. Pilihan jurusan pun cenderung seragam, berkumpul pada bidang-bidang yang dianggap “aman” dan memiliki prospek kerja konvensional seperti pendidikan, ekonomi, atau hukum. Akibatnya, terjadi fenomena oversupply lulusan di bidang tertentu, sementara sektor-sektor baru seperti teknologi, energi terbarukan, dan bioteknologi kekurangan tenaga ahli.
Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ketimpangan tenaga kerja, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam menumbuhkan diversifikasi minat dan bakat. Ketika orientasi belajar tidak memberi ruang eksplorasi lintas bidang, siswa kehilangan kesempatan untuk mengenali potensinya. Sebuah studi World Bank (2024) menunjukkan bahwa orientasi pembelajaran yang kaku memperkecil kemungkinan siswa untuk memilih karier non-tradisional dan memperlemah inovasi nasional. Dengan kata lain, sistem yang menuntut keseragaman justru melahirkan stagnasi.
Situasi ini diperparah oleh ketimpangan antarwilayah. Sekolah di daerah perkotaan memiliki akses ke teknologi dan sumber belajar modern, sementara sekolah di daerah tertinggal masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Akibatnya, kesenjangan mutu pendidikan semakin melebar. Data BPS (2024) menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil asesmen nasional antara wilayah timur dan barat Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada hasil akademik, tetapi juga memperlemah kohesi sosial dan mobilitas ekonomi antar generasi.
Pendidikan yang berorientasi hafalan juga menciptakan paradoks terhadap semangat Merdeka Belajar itu sendiri. Di satu sisi, pemerintah mendorong fleksibilitas, namun di sisi lain sistem evaluasi dan administrasi masih mengekang kebebasan berpikir. Guru yang mencoba inovatif sering kali terhambat oleh birokrasi atau kekhawatiran terhadap penilaian formal. Akibatnya, semangat merdeka berubah menjadi slogan tanpa substansi. Untuk keluar dari paradoks ini, dibutuhkan rekonstruksi menyeluruh terhadap sistem asesmen dan pelatihan guru.
Transformasi pendidikan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan kurikulum. Diperlukan perubahan budaya berpikir di ruang kelas. Guru harus berani melepas peran tradisional sebagai “pemberi informasi” dan mengambil peran sebagai “fasilitator pembelajaran”. Ini berarti memberi ruang bagi siswa untuk gagal, bertanya, dan menemukan jawaban sendiri. Ketika guru memberi kepercayaan kepada siswa untuk mengatur proses belajarnya, mereka sedang menumbuhkan karakter mandiri dan tangguh, dua kualitas utama untuk menghadapi abad pengetahuan.
Di sisi lain, dunia kerja masa kini menuntut kompetensi lintas disiplin. Seseorang tidak lagi cukup hanya menguasai satu bidang sempit, tetapi harus mampu berpikir sistemik, berkolaborasi, dan beradaptasi. Namun lulusan sekolah dan universitas di Indonesia masih membawa kebiasaan berpikir linear dan tertutup. Mereka pandai menghafal teori, namun kurang terlatih untuk mengintegrasikan ilmu dari berbagai bidang guna menyelesaikan masalah nyata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum menyiapkan lifelong learners, melainkan sekadar exam takers.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan pendidikan perlu bergeser dari teaching to the test menjadi learning for life. Pemerintah harus memperkuat ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, berbasis proyek, dan relevan dengan konteks lokal. Kurikulum Merdeka seharusnya menjadi wahana transformasi epistemologis, bukan hanya perubahan format. Guru perlu dilatih secara berkelanjutan melalui sistem mentoring dan learning community, bukan sekadar pelatihan singkat formalitas.
Selain itu, evaluasi pendidikan harus berorientasi pada proses dan pertumbuhan, bukan hanya hasil akhir. Asesmen diagnostik dan reflektif dapat membantu guru memahami perkembangan tiap siswa dan menyesuaikan pendekatan pengajaran. Penggunaan teknologi juga bisa mendukung diferensiasi pembelajaran tanpa mengorbankan nilai-nilai humanistik. Ketika pendidikan bergerak ke arah yang lebih reflektif, personal, dan bermakna, maka sistem pengetahuan yang dihasilkan akan lebih berdaya guna bagi kehidupan masyarakat luas.
Pada akhirnya, refleksi tentang pendidikan Indonesia bukan sekadar tentang kurikulum atau kebijakan, melainkan tentang paradigma manusia. Apakah sekolah akan terus mencetak penghafal, atau membentuk pemikir? Apakah siswa hanya akan mengejar nilai, atau mengejar makna? Pendidikan sejati seharusnya membebaskan manusia dari ketakutan akan kesalahan dan menuntun mereka untuk berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadaran. Jika setiap guru, siswa, dan pemimpin pendidikan mampu menanamkan semangat itu, maka kita tidak hanya akan memperbaiki sistem, tetapi juga membangun masa depan bangsa yang lebih merdeka dalam berpikir dan berkehidupan.