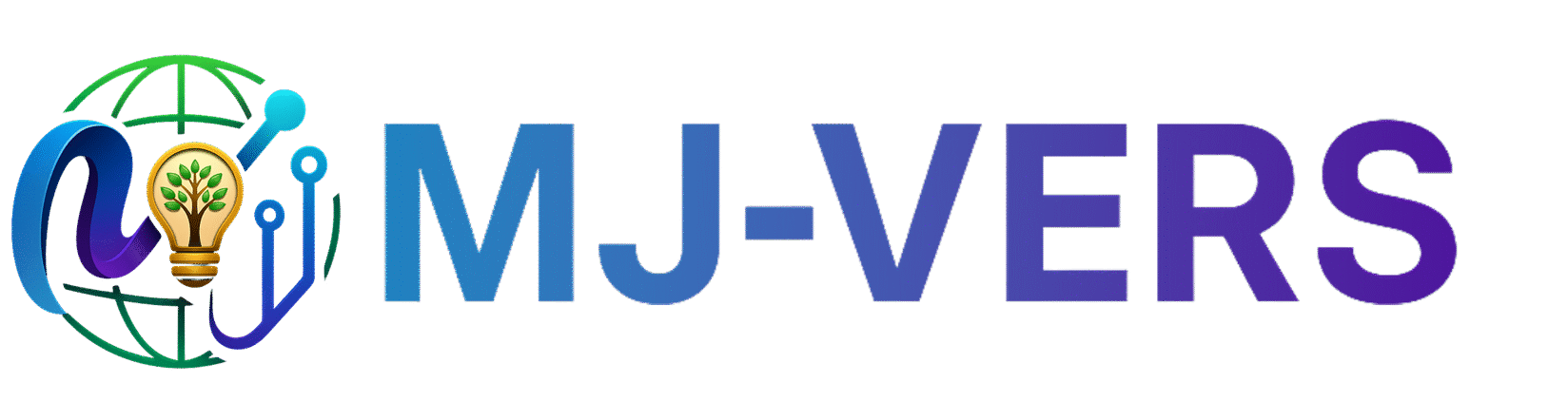Beberapa bulan terakhir, ruang publik Indonesia kembali diwarnai dengan berita tentang kekerasan di sekolah. Ada guru yang menampar murid karena dianggap tidak sopan, ada pula siswa yang menantang guru hingga berujung kekerasan verbal. Situasi ini menciptakan dilema moral dan hukum, ketika disiplin berubah menjadi kekerasan, dan ketika upaya mendidik justru berpotensi menjerat pendidik.
Fenomena ini bukan sekadar peristiwa individual, melainkan gejala sosial yang menunjukkan adanya ketegangan antara paradigma lama dan tuntutan baru dalam dunia pendidikan.
Di balik setiap tindakan kekerasan, terdapat ekosistem pendidikan yang sedang pincang. Banyak guru mengaku kehilangan pegangan antara menjadi pendidik yang lembut dan penegak disiplin yang tegas. Sistem pendidikan kita menuntut guru menjadi sosok ideal seperti penyabar, inspiratif, penuh empati, namun tanpa selalu memberikan dukungan pelatihan dan kesejahteraan yang memadai. Tekanan administratif, kurikulum yang padat, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi sering membuat guru bekerja dalam kondisi emosional yang rapuh.
Dari sisi siswa, kondisi tidak kalah kompleks. Generasi digital hari ini tumbuh dalam ruang sosial yang cair, dengan kebebasan berekspresi tanpa batas dan akses luas terhadap informasi. Mereka lebih kritis, lebih cepat bereaksi, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap hak-hak individu. Namun ironisnya, banyak yang kehilangan kemampuan dasar untuk mengelola emosi, menghormati otoritas, dan memahami konsekuensi sosial dari perilaku mereka. Ketidakhadiran teladan yang konsisten di rumah maupun di dunia maya memperburuk krisis karakter ini.
Akar persoalan ini tidak semata terletak pada guru atau siswa, melainkan pada struktur dan budaya pendidikan itu sendiri. Dalam banyak sekolah, disiplin masih dipahami sebagai kepatuhan yang lahir dari rasa takut, bukan kesadaran. Pendekatan yang digunakan masih bercorak hierarkis yaitu guru sebagai pengendali, siswa sebagai pihak yang dikendalikan. Padahal, paradigma pendidikan modern menekankan relasi setara antara pendidik dan peserta didik, sebuah relasi yang menumbuhkan tanggung jawab, bukan ketakutan.
Secara historis, warisan pendidikan kolonial dan militeristik meninggalkan jejak panjang dalam praktik sekolah kita. Guru dianggap “pahlawan” yang harus dihormati tanpa syarat, sementara siswa wajib tunduk tanpa banyak bertanya. Pandangan ini, meski tampak disiplin, sesungguhnya mengandung benih kekerasan simbolik, karena mengabaikan hak anak untuk berpikir, bertanya, dan mengekspresikan diri. Ketika sistem seperti ini berhadapan dengan generasi yang terbiasa menegosiasikan otoritas, benturan hampir tak terhindarkan.
Faktor lain yang memperparah situasi adalah ketidakjelasan regulasi tentang batas antara “penegakan disiplin” dan “kekerasan.” Undang-Undang Perlindungan Anak jelas melarang kekerasan fisik maupun psikis terhadap siswa, namun di sisi lain, banyak sekolah belum memiliki mekanisme internal yang transparan untuk menangani pelanggaran perilaku. Akibatnya, guru sering berjalan di atas tali tipis, yaitu satu tindakan keras bisa dianggap kekerasan, tetapi ketidaktegasan juga dianggap kelemahan.
Secara psikologis, guru dan siswa sama-sama berada di bawah tekanan emosional. Guru yang lelah cenderung kehilangan kemampuan regulasi diri, sementara siswa yang frustasi mencari perhatian melalui perilaku menantang. Dalam kondisi ini, komunikasi empatik mudah runtuh. Fenomena ini sejalan dengan temuan psikologi pendidikan modern yang menegaskan bahwa stres kronis menurunkan kapasitas empati dan meningkatkan kecenderungan agresif, baik pada orang dewasa maupun anak-anak.
Jika akar masalahnya kompleks, maka solusinya pun harus bersifat sistemik. Langkah pertama adalah mengubah paradigma disiplin di sekolah. Disiplin tidak boleh lagi diartikan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial-emosional. Guru tidak menghukum, tetapi membantu siswa memahami akibat dari tindakannya dan memperbaikinya. Pendekatan ini dikenal dengan istilah restorative discipline, pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan, bukan pembalasan.
Model restorative justice di dunia pendidikan sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Selandia Baru, Kanada, dan Finlandia. Dalam pendekatan ini, setiap pelanggaran diselesaikan melalui dialog antara pihak yang dirugikan dan pelaku, dengan pendampingan guru atau konselor. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan tanggung jawab moral. Studi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan model ini mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kekerasan dan drop-out siswa (Hopkins, 2018; Morrison, 2020).
Indonesia sebenarnya memiliki fondasi kuat untuk mengadopsi pendekatan serupa. Nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan ngerti-ngroso-nglakoni dalam budaya Jawa sejalan dengan semangat restorative justice. Namun sayangnya, potensi ini belum banyak diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan nasional. Sekolah lebih sering mengandalkan sanksi administratif ketimbang dialog pemulihan. Padahal, pendidikan berbasis nilai seharusnya menumbuhkan karakter empatik, bukan sekadar menakut-nakuti.
Langkah kedua adalah membekali guru dengan keterampilan sosial-emosional (Social Emotional Learning/SEL). Banyak guru yang tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mengelola emosi diri atau merespons perilaku siswa secara asertif. Padahal, penelitian menunjukkan guru yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih efektif dalam mendisiplinkan tanpa kekerasan. Dengan pelatihan SEL, guru dapat menumbuhkan empati tanpa kehilangan wibawa.
Langkah ketiga adalah melibatkan orang tua dan komunitas. Banyak kasus kekerasan di sekolah berakar dari lingkungan rumah yang juga keras. Anak yang terbiasa dipukul akan menganggap kekerasan sebagai bahasa normal. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak bisa berhenti di sekolah. Orang tua harus menjadi mitra aktif dalam membangun budaya empati. Sekolah perlu membuka ruang komunikasi yang transparan, bukan hanya ketika terjadi masalah, tetapi juga dalam keseharian.
Langkah keempat adalah memperkuat sistem perlindungan hukum yang seimbang antara hak siswa dan hak guru. Kekerasan terhadap siswa memang harus dihentikan, tetapi kriminalisasi berlebihan terhadap guru juga harus dicegah. Negara perlu menyediakan mekanisme mediasi dan pendampingan hukum yang adil agar guru tidak merasa ditinggalkan ketika menghadapi kasus di lapangan. Perlindungan ganda ini penting agar sekolah tidak kehilangan otoritas moralnya.
Selain perubahan sistem dan pelatihan, perlu juga ada transformasi budaya pendidikan. Masyarakat harus berhenti memandang kekerasan sebagai “bagian dari didikan.” Pendidikan sejati tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari rasa dihargai. Guru yang dihormati bukan karena ditakuti, melainkan karena ia menjadi teladan dalam mengelola diri dan memahami orang lain. Begitu pula siswa, mereka belajar menjadi manusia bukan karena takut pada sanksi, tapi karena sadar pada nilai.
Kekerasan di sekolah adalah panggilan bagi kita semua untuk meninjau kembali arah pendidikan nasional. Apakah sekolah kita sedang menumbuhkan manusia beradab, atau sekadar memproduksi kepatuhan semu? Membangun pendidikan yang manusiawi berarti menumbuhkan disiplin yang berbasis kesadaran, bukan paksaan, menghormati tanpa menindas dan mengajar tanpa melukai. Restorasi pendidikan Indonesia bukan hanya tugas guru, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa yang ingin masa depan tumbuh tanpa takut.