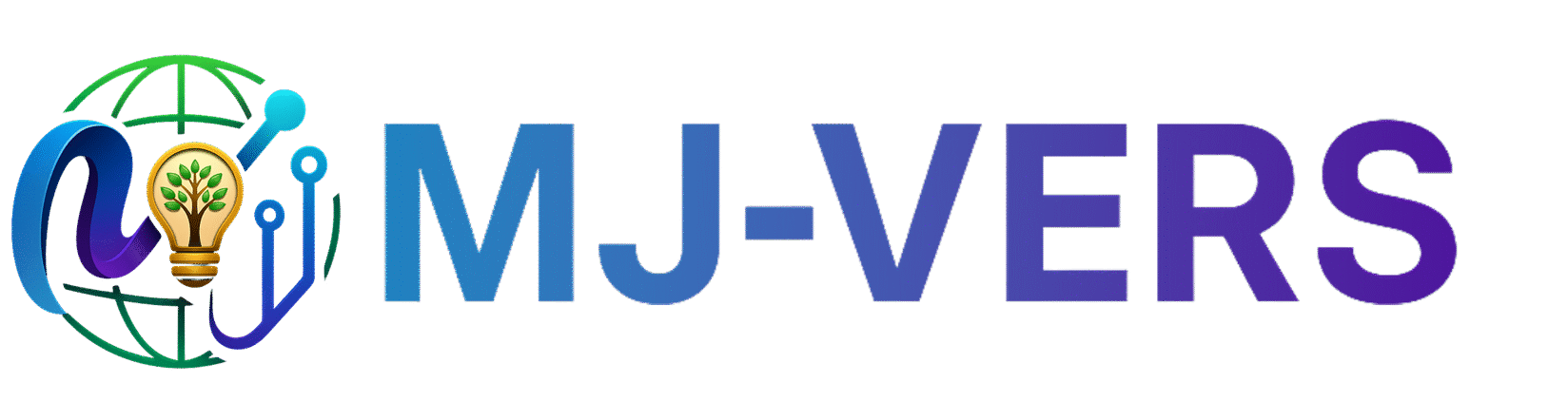Gelombang protes yang memuncak hingga berujung pada aksi destruktif terhadap kediaman sebagian tokoh publik baru-baru ini, merefleksikan puncak dari kemarahan rakyat. Fenomena tersebut bukan sekadar tindak spontan, melainkan hasil akumulasi kekecewaan panjang terhadap perilaku elite politik yang dinilai tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
James C. Scott dalam Weapons of the Weak (1985) menyebut, akumulasi tekanan sosial yang lama terpendam sering kali menemukan salurannya dalam bentuk perlawanan terbuka ketika batas kesabaran rakyat terlampaui.
Kemarahan publik ini dipicu oleh banyak faktor, antara lain kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi rakyat, hingga simbol-simbol gaya hidup elite yang menegaskan jurang antara wakil rakyat dan konstituennya. Pierre Bourdieu dalam Distinction (1984) menekankan bahwa gaya hidup elite bukan sekadar persoalan selera, tetapi juga instrumen kekuasaan yang dapat melukai rasa keadilan sosial ketika ditampilkan di ruang publik.
Momentum tragis yang menimpa seorang warga dalam unjuk rasa menambah beban emosional dan menjadi titik balik bagi eskalasi protes. Charles Tilly dalam From Mobilization to Revolution (1978) menjelaskan, seringkali “kejadian pemicu” inilah yang mengubah ketidakpuasan laten menjadi ledakan kolektif yang eksplosif.
Aksi massa terhadap properti milik sebagian elite politik juga dapat dibaca sebagai pesan simbolis, bahwa rakyat tidak hanya marah pada kebijakan, tetapi juga pada representasi gaya hidup elite yang dianggap kontras dengan realitas mayoritas. Hannah Arendt dalam On Violence (1970) mengingatkan bahwa kekerasan sering muncul bukan karena kekuatan, melainkan karena rapuhnya legitimasi otoritas.
Fenomena ini memperlihatkan krisis representasi dalam demokrasi perwakilan. Joseph Schumpeter dalam Capitalism, Socialism and Democracy (1942) menekankan, demokrasi hanya akan sehat jika wakil rakyat sungguh-sungguh menjalankan peran representatifnya. Ketika peran ini tergerus oleh kepentingan pribadi atau simbol-simbol kemewahan, demokrasi kehilangan fondasi moralnya.
Selain itu, dalam budaya politik Indonesia, simbol-simbol yang ditampilkan oleh elite punya makna yang sangat kuat. Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) menjelaskan bahwa simbol merupakan medium komunikasi nilai. Ketika simbol yang ditunjukkan elite berseberangan dengan rasa keadilan publik, yang muncul adalah kekecewaan dan krisis kepercayaan.
Meski demikian, aksi destruktif seperti penyerangan dan penjarahan tidak dapat dijadikan solusi atas krisis representasi. Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) mengingatkan bahwa pembangunan demokrasi harus bertumpu pada kebebasan substantif, yaitu kebebasan yang memberi ruang pada partisipasi rakyat tanpa meniadakan norma hukum dan moral.
Kondisi ini juga dapat dibaca sebagai keretakan kontrak sosial. Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762) menekankan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari kesesuaian dengan kehendak umum (general will). Jika wakil rakyat gagal mencerminkan kehendak itu, kontrak sosial mengalami krisis dan masyarakat mencari cara lain untuk menyalurkan aspirasi.
Dengan demikian, yang kita saksikan adalah bukan sekadar kerusuhan, melainkan krisis kepercayaan. Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995) menyatakan, masyarakat hanya bisa berkembang bila ada modal sosial berupa kepercayaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik adalah peringatan serius bagi keberlangsungan demokrasi.
Refleksi yang perlu diambil adalah perlunya perbaikan etika politik dari elite sekaligus kedewasaan ekspresi politik dari rakyat. Dari sisi rakyat, aspirasi seharusnya disalurkan dalam koridor hukum dan moral. Dari sisi elite, tuntutannya lebih besar, mengembalikan politik kepada akarnya sebagai amanah dan pelayanan publik. Nurcholish Madjid dalam Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (1987) mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab. Tanpa kesadaran ini, demokrasi hanya akan menjadi panggung konflik tanpa solusi.