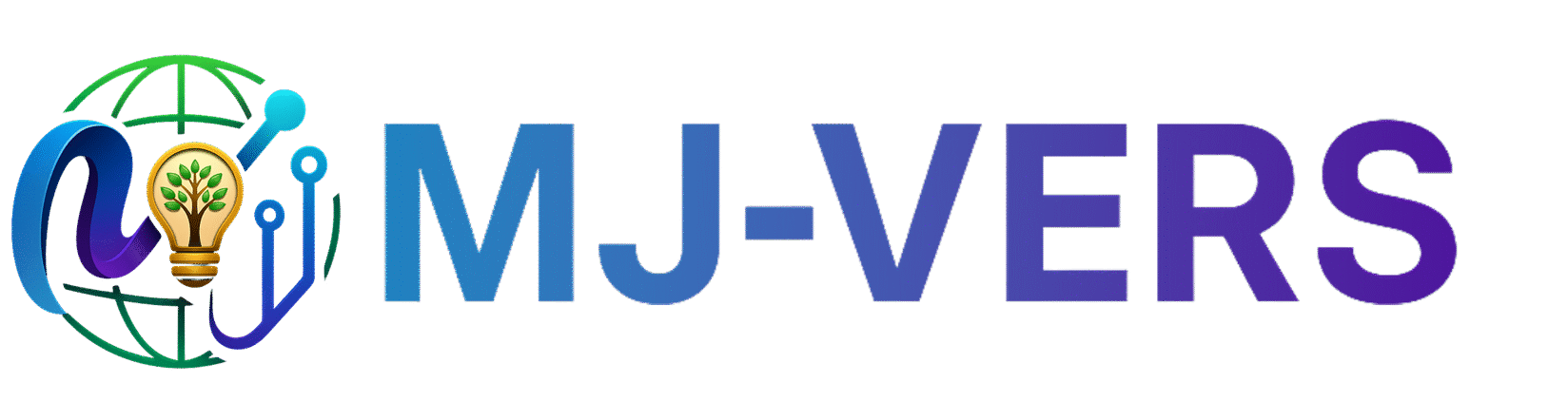Suatu hari, di antara riuh rutinitas mengajar di Boarding School SMPIT LHI Bantul, Yogyakarta, saya mendapati sebuah galon air telah kosong. Hanya sebuah kebutuhan sepele, namun di balik kosongnya wadah itu, tersimpan rahasia yang lebih dalam, seperti sumur jiwa yang mengingatkan bahwa tidak semua kekosongan adalah sia-sia. Kadang, di ruang-ruang sederhana, Allah menyelipkan hikmah-Nya dengan cara yang paling halus, seperti angin yang berbisik lewat dedaunan.
Dengan lirih saya meminta tolong kepada dua santri yang kebetulan melintas. Seolah semesta menyiapkan panggung kecil, Allah mengatur dua wajah muda itu sebagai cermin dari pilihan hati manusia. Satu peristiwa sederhana, namun terasa bagai ketukan halus di pintu kesadaran, mengingatkan bahwa hidup seringkali menyingkap kebenaran lewat hal-hal yang kita anggap remeh.
Santri pertama menatap sejenak, lalu dengan jujur berkata ia tak bisa membantu, sebab ia telah janjian bersama teman nya untuk bermain basket. Senyumnya sopan, matanya meminta pengertian. Saya mengangguk, berusaha memahami, meski di sudut hati ada bayang kecewa. Bukan karena ia menolak, melainkan karena ia meletakkan permainan di atas panggilan kepedulian. Seperti bunga yang memilih menutup kelopaknya saat matahari masih bersinar, kehilangan momen indah yang seharusnya bisa ia reguk.
Tak lama berselang, santri kedua datang dengan wajah cerah bagaikan fajar yang baru menyingkapkan cahaya. Bahkan sebelum kata sempat terucap, ia sudah menawarkan diri untuk membantu. Tangannya ringan, langkahnya ringan, hatinya lebih ringan lagi. Ia mengganti galon yang kosong itu tanpa keluh, seakan air yang mengalir di dalamnya turut menjadi doa yang sunyi. Di situlah, saya merasa disentuh oleh pelajaran yang tak akan pernah tertulis di buku manapun.
Waktu berjalan, namun wajahnya melekat di ingatan saya. Bukan semata karena ia menolong, melainkan karena tulusnya getar hati yang ia tunjukkan. Setiap kali ia meminta izin atau pertolongan, hati saya lebih mudah luluh. Bukan karena pilih kasih, tapi karena jiwa saya mengenali siapa yang benar-benar hadir ketika dipanggil. Seperti bumi yang mengingat siapa yang menanam benih dengan cinta.
Lalu saya merenung, tidakkah kita semua sedang memainkan peran yang sama di hadapan Allah? Seringkali ketika panggilan-Nya datang, kita menundanya. Kita berkata dalam hati “Tunggu, ya Rabb… izinkan aku menyelesaikan urusanku lebih dulu.” Kita bernegosiasi dengan waktu, menunda sujud, menangguhkan kebaikan, seolah detik-detik yang kita genggam adalah milik kita, padahal semuanya hanyalah titipan.
Kita lupa, bahwa Allah tidak membutuhkan kita. Justru kitalah yang merintih tanpa-Nya. Dan ketika ada hamba yang bergegas memenuhi panggilan, yang ringan dalam memberi, yang cepat dalam sujud, maka langit pun merekam namanya. Mereka akan dijaga doanya, dilapangkan jalannya, seperti hujan yang tak pernah pelit menyuburkan tanah.
Betapa sering kita hanya mengetuk pintu Allah saat sempit, namun berpaling saat lapang. Kita datang dengan wajah basah air mata, tetapi menolak ketika diminta sekadar menebar senyum dan ringan tangan. Padahal, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui siapa yang mencintai-Nya dengan jujur, bukan sekadar mencari-Nya saat terluka.
Saya belajar dari dua santri itu, bahwa ketulusan dalam perkara kecil adalah gema dari kedalaman jiwa. Allah pun menilai kita bukan dari besarnya amal, melainkan dari beningnya niat. Kedekatan dengan-Nya tidak dibangun dari langkah raksasa, tetapi dari jejak-jejak kecil yang kita tempuh tanpa menunda.
Maka sejak hari itu, saya ingin menjadi seperti santri kedua, ringan hati, ringan langkah, dan ringan tangan. Karena saya percaya, jalan orang-orang yang ringan dalam ketaatan akan selalu dilapangkan Allah. Dan semoga kelak, ketika tangan ini terangkat dalam doa, langit mengenang saya sebagaimana saya mengenang santri itu dengan senyum, dengan cinta, dan dengan kemurahan yang mengalir deras, sebab dahulu saya bergegas menjawab panggilan-Nya.