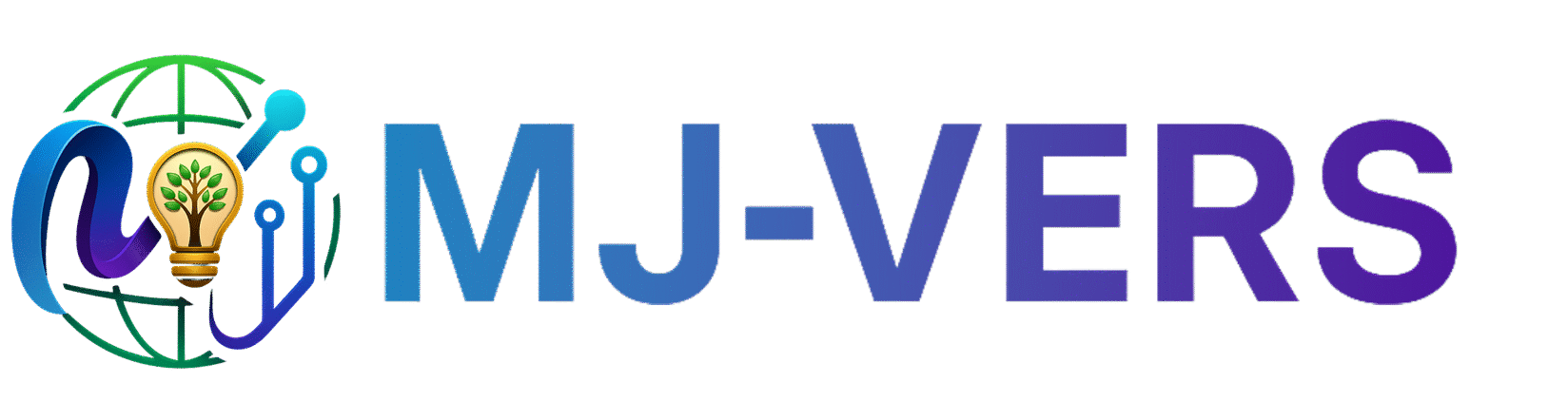Beberapa waktu terakhir, ruang publik kembali diguncang oleh isu sensitif yaitu beredarnya potongan video yang memuat narasi seolah-olah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa “gaji guru adalah beban negara”. Potongan tersebut viral, memantik kemarahan banyak kalangan, terutama para pendidik.Namun, setelah diverifikasi, narasi itu ternyata hasil deepfake dan pemotongan konteks. Meski demikian, isu ini membuka ruang refleksi penting mengapa peran guru kerap direduksi hanya dalam kerangka beban fiskal, bukan investasi jangka panjang bangsa?
Dalam perspektif Islam, guru ditempatkan pada posisi yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang guru” (HR. Ibnu Majah). Posisi guru sebagai penyampai ilmu tidak hanya bermakna transfer pengetahuan, tetapi juga pembentuk akhlak, peradaban, dan arah hidup masyarakat. Karenanya, menyebut guru sebagai “beban” adalah bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang menempatkan ilmu dan pengajarnya pada derajat yang tinggi.
Dalam sejarah Indonesia, guru memiliki peran vital sejak sebelum kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara dan para tokoh pergerakan menanamkan nilai kebangsaan melalui pendidikan. Pada masa kemerdekaan, guru menjadi motor literasi politik dan nasionalisme. Pasca kemerdekaan, guru mengisi ruang kosong pembangunan bangsa dengan mengajar di desa-desa, meski dengan gaji yang sangat terbatas. Hingga kini, guru tetap berdiri di garda depan, meski sering kali kesejahteraannya tertinggal jauh dibanding tanggung jawabnya. Jika kita kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban negara. Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN adalah bentuk komitmen konstitusional, bukan sekadar pilihan teknokratis. Oleh karena itu, menanggung kesejahteraan guru bukanlah “kedermawanan negara” melainkan konsekuensi logis dari janji konstitusi.
Filsafat pendidikan pun menegaskan hal yang sama. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menolak pandangan pendidikan sebagai proses mekanis. Baginya, pendidikan adalah pembebasan manusia. Guru, dalam hal ini, bukan sekadar pekerja bergaji, melainkan aktor utama dalam mengubah kesadaran. Maka, jika guru dianggap beban, sesungguhnya bangsa sedang merendahkan fondasi peradabannya sendiri. Dalam teori keadilan distributif John Rawls, negara berkewajiban memberikan perlakuan khusus pada kelompok strategis yang menopang keberlangsungan keadilan sosial. Guru, dengan tanggung jawab mencetak sumber daya manusia, masuk dalam kategori itu. Jika kesejahteraan mereka dilemahkan, maka dampaknya bukan hanya pada guru itu sendiri, tetapi juga pada kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.
Isu kesejahteraan guru di Indonesia memang masih menjadi tantangan. Data menunjukkan, gaji guru di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Guru di Finlandia, misalnya, digaji setara dengan profesi prestisius lain, karena negara memahami bahwa kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pengajar. Di Indonesia, guru honorer masih banyak yang menerima upah jauh di bawah UMR. Inilah realitas yang justru membuat publik sensitif ketika ada narasi yang merendahkan martabat guru. Fakta di lapangan memperlihatkan kesenjangan gaji guru di Indonesia dengan negara lain sangat mencolok. Gaji guru PNS pemula rata-rata hanya sekitar Rp3 juta per bulan, sementara di negara OECD gaji guru menengah dengan pengalaman belasan tahun bisa mencapai setara Rp60–70 juta per bulan. Ketertinggalan ini memperlebar jurang daya saing pendidikan Indonesia dibandingkan dunia internasional.
 Meskipun pernyataan “guru beban negara” terbukti hoax, fakta bahwa isu tersebut mudah dipercaya menunjukkan adanya ketidakpuasan kolektif atas penghargaan negara terhadap profesi guru. Hoax ini menyebar karena menyentuh luka lama, yaitu kesenjangan antara retorika penghargaan terhadap guru dan kenyataan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kritik bukan hanya diarahkan pada sosok individu, tetapi pada sistem yang masih menempatkan guru dalam posisi marjinal. Lebih jauh, kasus viral ini bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya literasi digital. Teknologi deepfake kini mampu memanipulasi suara dan wajah tokoh publik, sehingga masyarakat mudah terkecoh. Namun, alih-alih berhenti pada persoalan hoax, kita perlu menjadikannya momentum untuk merefleksikan betapa rapuhnya posisi guru dalam imajinasi kebangsaan kita. Jika isu semacam ini bisa begitu cepat dipercaya, itu artinya masyarakat sudah lama menganggap guru memang diperlakukan sebagai beban, bukan aset.
Meskipun pernyataan “guru beban negara” terbukti hoax, fakta bahwa isu tersebut mudah dipercaya menunjukkan adanya ketidakpuasan kolektif atas penghargaan negara terhadap profesi guru. Hoax ini menyebar karena menyentuh luka lama, yaitu kesenjangan antara retorika penghargaan terhadap guru dan kenyataan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kritik bukan hanya diarahkan pada sosok individu, tetapi pada sistem yang masih menempatkan guru dalam posisi marjinal. Lebih jauh, kasus viral ini bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya literasi digital. Teknologi deepfake kini mampu memanipulasi suara dan wajah tokoh publik, sehingga masyarakat mudah terkecoh. Namun, alih-alih berhenti pada persoalan hoax, kita perlu menjadikannya momentum untuk merefleksikan betapa rapuhnya posisi guru dalam imajinasi kebangsaan kita. Jika isu semacam ini bisa begitu cepat dipercaya, itu artinya masyarakat sudah lama menganggap guru memang diperlakukan sebagai beban, bukan aset.
Guru seharusnya ditempatkan sebagai investasi strategis bangsa. Dalam terminologi ekonomi pembangunan, pendidikan bukanlah konsumsi, melainkan capital formation. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk guru akan kembali berlipat ganda melalui kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Negara-negara maju tidak pernah menghitung guru sebagai beban, melainkan sebagai motor produktivitas nasional. Maka, alih-alih terjebak pada perdebatan tentang benar-tidaknya ucapan seorang pejabat, kita perlu mengarahkan energi publik pada advokasi struktural, yaitu bagaimana memastikan guru mendapat kesejahteraan yang layak, penghormatan sosial, serta ruang untuk berkembang secara profesional. Sebab, hanya dengan guru yang sejahtera lahir murid yang berkarakter, berpengetahuan, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Akhirnya, isu viral ini memberi dua pelajaran. Pertama, bahwa masyarakat harus semakin kritis dalam menyikapi arus informasi digital. Kedua, bahwa bangsa ini tidak boleh lagi menunda pembenahan nasib guru. Karena jika guru terus diperlakukan sebagai beban, maka sejatinya yang sedang kita bebani adalah masa depan kita sendiri.