 Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.5/B/HK.03.01/2025 tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (KA) bagi guru patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan di era digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis, terutama dari segi implementasi dan kesiapan lapangan.
Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.5/B/HK.03.01/2025 tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (KA) bagi guru patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan di era digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis, terutama dari segi implementasi dan kesiapan lapangan.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin lincahnya generasi muda dalam menggunakan perangkat digital, dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi. Salah satu wacana yang berkembang adalah pentingnya penguasaan coding oleh para guru. Coding dianggap sebagai keterampilan dasar abad 21 yang dapat memperkuat literasi digital dan kreativitas dalam pembelajaran. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua guru harus belajar coding, dan kapan waktu terbaik untuk membekali mereka. Fakta dalam praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki latar belakang teknologi yang memadai, banyak guru saat ini masih berjuang untuk menguasai teknologi dasar, seperti penggunaan LMS, pengelolaan dokumen digital, atau pembuatan media ajar interaktif. Guru kelas, terutama di jenjang SD dan SMP, memiliki peran sebagai pendidik multidisiplin yang lebih banyak berkutat pada penguatan karakter dan pembelajaran tematik.
Memberikan beban tambahan berupa pelatihan coding bagi mereka tanpa memperhatikan kondisi riil dapat berdampak negatif terhadap efektivitas peran mereka. Ketika mereka diminta untuk belajar coding, yang merupakan tingkat lanjut dalam kompetensi TIK, tak jarang muncul kebingungan, resistensi, bahkan kelelahan. Hal ini wajar, mengingat tuntutan administrasi, beban kerja, dan ritme tugas guru yang tidak ringan. Risiko lainnya adalah terciptanya kesenjangan keterampilan antar guru. Guru yang melek teknologi akan dengan mudah mengikuti pelatihan, sementara guru yang belum familiar bisa merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan diri. Padahal, semangat digitalisasi seharusnya membangun kolaborasi, bukan kompetisi internal di antara tenaga pendidik.
Solusi jangka panjang seharusnya dimulai dari hulu, yaitu memasukkan coding, AI, dan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum program pendidikan guru (LPTK). Calon guru yang dibekali sejak kuliah tentu akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, tanpa harus dikejar dengan pelatihan teknis saat mereka sudah menjadi guru. Sejalan dengan itu, Prof. Suyanto, M.Ed., Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, pernah menyampaikan bahwa “transformasi digital pendidikan tidak cukup dilakukan di hilir. Lembaga pendidikan guru harus menjadi motor awal perubahan agar adaptasi teknologi tidak membebani, tapi memberdayakan” (Sumber: Webinar Transformasi Digital Pendidikan, UNY, 12 Oktober 2022). Kutipan ini menguatkan pentingnya perubahan struktural dalam sistem pendidikan guru.
Untuk guru yang saat ini aktif mengajar, pendekatan alternatif yang lebih praktis perlu disiapkan. Tidak semua inovasi pembelajaran harus diawali dengan coding. Banyak platform yang dapat dimanfaatkan oleh guru tanpa perlu memahami bahasa pemrograman, seperti Canva for Education, Wordwall, Liveworksheet, dan berbagai alat bantu AI. Fokusnya bukan pada “mampu coding atau tidak”, tapi pada sejauh mana guru bisa menggunakan teknologi untuk mempermudah dan memperkaya proses belajar mengajar. Pemerintah sebaiknya tidak menyeragamkan pelatihan coding kepada semua guru. Cukup beberapa guru ditunjuk sebagai penggerak digital sekolah, mereka inilah yang bisa mendampingi rekan sejawat secara lebih efektif dan manusiawi. Strategi ini jauh lebih aplikatif daripada memaksa semua guru menguasai keterampilan yang belum tentu sesuai dengan konteks tugas mereka.
Selain itu, waktu adalah faktor penting. Jika guru baru mulai belajar coding sekarang, kapan mereka akan sempat menerapkan inovasi di kelas? Digitalisasi adalah kebutuhan mendesak. Maka dari itu, jalur cepat (fast track) berbasis solusi digital non-coding perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan yang ada. Meskipun surat keputusan menyebut bahwa pelatihan ini ditujukan untuk guru kelas dan guru informatika, perlu dipahami bahwa kelompok ini sangat berbeda. Guru informatika memiliki kompetensi teknis sebagai bagian dari profesinya, sedangkan guru kelas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks. Menyamakan kebutuhan pelatihan untuk dua kelompok ini adalah bentuk penyederhanaan yang kurang tepat.
Di daerah 3T, keterbatasan infrastruktur, perangkat, dan akses internet memperparah tantangan. Pelatihan coding tanpa dukungan infrastruktur hanya akan menambah daftar panjang program yang gagal mencapai sasarannya. Kebijakan teknologi harus sensitif terhadap ketimpangan akses dan kondisi geografis. Jika coding dianggap sebagai keterampilan penting di masa depan, seharusnya pendekatan pendidikan kita mulai bergeser. Jika coding memang dianggap penting dan strategis untuk mendukung transformasi pembelajaran, maka transformasi harus disiapkan sejak jenjang pendidikan calon guru, yakni di bangku kuliah pada program studi keguruan. Dengan demikian, calon guru sudah memiliki bekal sebelum terjun ke lapangan. Kurikulum LPTK perlu didesain ulang, bukan hanya menambahkan pelatihan insidental bagi guru yang sudah aktif mengajar.
Membekali mahasiswa pendidikan dengan keterampilan coding akan memberikan ruang eksplorasi yang lebih luas dan waktu yang lebih memadai. Mereka bisa belajar tidak hanya tentang sintaksis dan logika pemrograman, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan coding dalam konteks pedagogi. Hal ini akan membentuk calon pendidik yang tidak hanya teknis, tapi juga reflektif dan inovatif. Lebih jauh lagi, memasukkan coding dalam kurikulum keguruan akan memberikan efisiensi jangka panjang. Biaya dan energi yang selama ini digunakan untuk pelatihan pascasertifikasi dapat dialihkan untuk penguatan kompetensi lanjutan atau pengembangan komunitas pembelajaran digital. Dengan kata lain, kita tidak terus-menerus menambal kekurangan, melainkan membangun dari hulu.
Sudah saatnya pemerintah, kampus, dan penyusun kebijakan pendidikan memikirkan ulang sistem pembinaan guru. Kita tidak bisa terus-menerus melempar tanggung jawab ke lapangan tanpa memperkuat fondasi dari lembaga penghasil guru. Membekali mahasiswa dengan coding adalah langkah strategis dan preventif untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Refleksi ini menjadi ajakan bagi kita semua, mari bangun perubahan dari akarnya. Jika coding memang menjadi bagian dari masa depan pembelajaran, maka tanamkan ia di tempat yang tepat, dalam kurikulum keguruan, bukan sebagai beban tambahan setelah guru terjun di medan. Karena inovasi tidak lahir dari paksaan, tapi dari kesiapan, dukungan, dan strategi yang bijak.
Selain pembenahan kurikulum, ekosistem digital di sekolah juga harus dibangun. Guru perlu ruang kolaboratif, komunitas belajar, dan insentif agar bisa berinovasi bersama. Dalam konteks ini, bukan semua guru harus jago coding, melainkan semua guru diberi akses dan dukungan agar mampu menciptakan pembelajaran yang relevan secara digital. Penting pula untuk menyediakan pelatihan yang berfokus pada kebutuhan nyata guru di lapangan, seperti penggunaan AI dalam menyusun RPP, pembuatan media ajar interaktif tanpa coding, dan pengelolaan kelas digital. Pendekatan ini jauh lebih membumi dan memberikan hasil yang langsung terasa.Dalam wawancaranya dengan Harian Kompas (17 Agustus 2023), Dr. M. Faizal, pengamat pendidikan teknologi, menyebutkan bahwa “tantangan pendidikan digital bukan pada penguasaan teknologi tinggi, tapi pada akses dan konteks. Guru harus diajak berpikir digital, bukan dipaksa menjadi programmer.”
Inti dari semua ini adalah bahwa transformasi pendidikan digital tidak bisa dilakukan secara seragam. Perlu strategi bertahap dan multi-jalur. Coding penting, tapi bukan satu-satunya jalan. Yang lebih utama adalah memastikan setiap guru punya peran dan cara untuk ikut serta dalam menciptakan pendidikan masa depan. Kebijakan pelatihan coding dan AI berdasarkan SK Dirjen GTK No.5/B/HK.03.01/2025 yang menyasar guru kelas dan guru informatika, masih perlu dikritisi. Meskipun guru informatika cenderung memiliki bekal dasar, banyak guru kelas, terutama di SD dan SMP belum memiliki kesiapan teknis yang memadai. Maka penyamarataan kebijakan ini bisa menciptakan kesenjangan capaian dan beban kerja yang tidak adil antar guru.
Daripada membebani semua guru dengan pelatihan yang sama, akan lebih bijak bila sekolah diberi ruang membentuk tim teknologi dan inovasi pembelajaran, yang terdiri dari guru-guru dengan minat dan kompetensi digital. Tim ini bisa menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus tempat belajar rekan-rekan sejawat yang lain. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya terasa adil, tapi juga lebih berdampak dan berkelanjutan. Tulisan ini bukan bentuk penolakan terhadap pelatihan coding, melainkan ajakan untuk menata ulang strategi transformasi digital pendidikan dengan cara yang lebih manusiawi, realistis, dan berdampak nyata.
Author: Marta Jaya,S.Pd.,M.Pd.
Menyukai ini:
Suka Memuat...
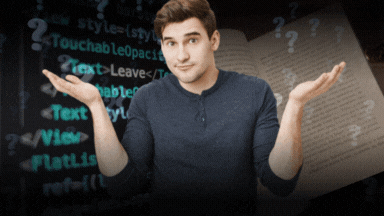 Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.5/B/HK.03.01/2025 tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (KA) bagi guru patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan di era digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis, terutama dari segi implementasi dan kesiapan lapangan.
Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.5/B/HK.03.01/2025 tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (KA) bagi guru patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan di era digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis, terutama dari segi implementasi dan kesiapan lapangan.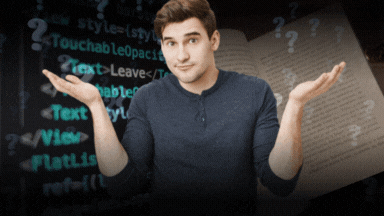 Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.5/B/HK.03.01/2025 tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (KA) bagi guru patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan di era digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis, terutama dari segi implementasi dan kesiapan lapangan.
Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.5/B/HK.03.01/2025 tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (KA) bagi guru patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan di era digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis, terutama dari segi implementasi dan kesiapan lapangan.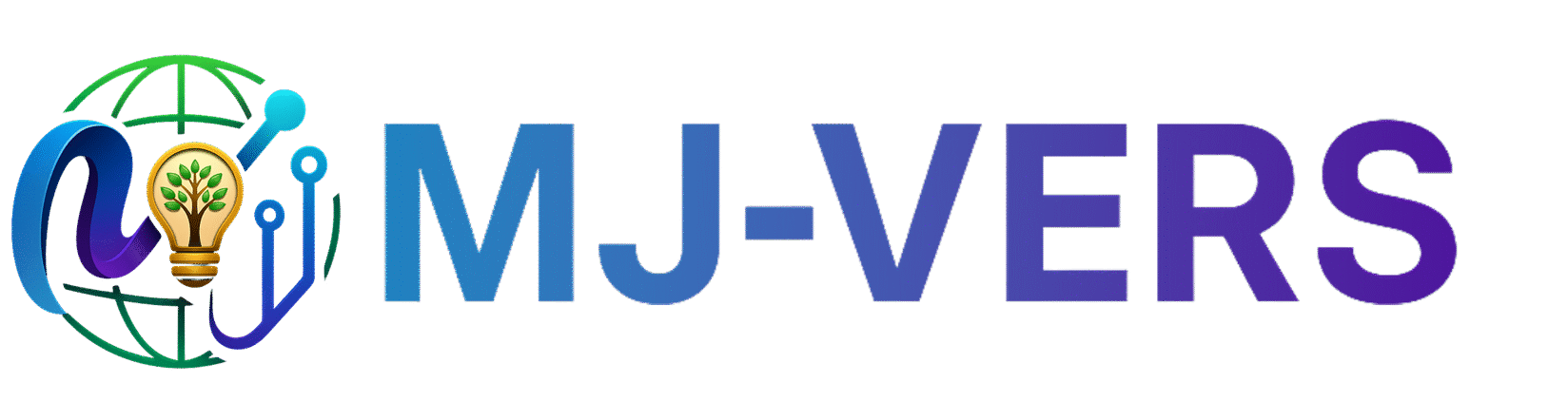












Tinggalkan Balasan